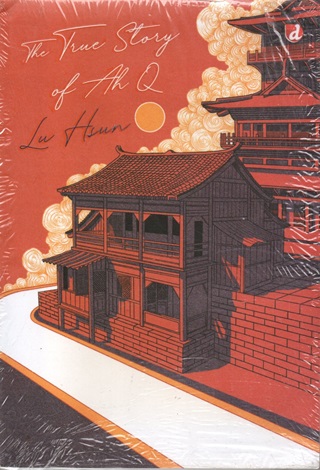Dalam masyarakat yang menjadikan kemampuan retorika sebagai salah satu ukuran intelektualitas seseorang, seperti di Amerika Serikat, kepiawaian berpidato dan berdebat menjadi sangat bernilai. Lantaran itu, merosotnya kualitas pidato—bukan menebar jargon, mengumbar janji, atau kata-kata muluk—dapat menjadi indikasi atau petunjuk awal tentang menurunnya kualitas pikir sebuah kelompok masyarakat.
Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh Elvin T. Lim dalam bukunya, The Anti-Intellectual Presidency: The Decline of Presidential Rhetoric From George Washington to George W. Bush. Lim meneliti pidato para presiden AS mengenai berbagai isu.
Dalam pidato-pidato itu, Lim menemukan bahwa kalimat-kalimat yang digunakan para presiden dari masa yang belakangan (Lim meneliti hingga masa George W. Bush) ternyata semakin pendek, kian miskin metafor, diksinya bertambah sederhana, dan kata-kata hampa semakin bertebaran. Ini menandakan, menurut Lim, kadar intelektualitas para pemimpin AS semakin berkurang.
Namun anehnya, George W. Bush terpilih dua kali dalam pemilihan presiden AS. Situasi inilah yang mengusik George Soros: “Apa yang salah dengan Amerika? Apa yang salah dengan kita?” Dalam bukunya, The Age of Fallibility, Soros menyebutkan bahwa pemerintahan George W. Bush mengeksploitasi peristiwa traumatis 11 September (9/11) untuk menancapkan ketakutan di dalam benak publik—sejenis “politik ketakutan”.
Dengan cara ini, publik menerima tanpa sikap kritis kebijakan-kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu membahayakan masyarakat AS sendiri. Masyarakat tidak lagi peduli pada upaya menemukan kebenaran. Delapan tahun terakhir masa pemerintahan Bush mewakili apa yang disebut “masa tidurnya nalar” (the sleep of reason).
Metafor tersebut meringkaskan situasi ketika masyarakat malas atau malah takut untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Alih-alih memikirkan dan menawarkan alternatif kebijakan bagi pemerintahnya, bersikap kritis pun enggan. Apa lagi ketika kritik kepada pemerintah disepadankan dengan sikap tidak patriotik, atau bersikap kritis kepada pemerintah berarti menentang negara.
Masyarakat Amerika saat ini, menurut Soros dalam bukunya, telah berkembang menjadi feel-good society, masyarakat yang sudah merasa nyaman dengan situasinya saat ini, yang enggan berpikir yang rumit-rumit, dan malas menjangkau kemungkinan-kemungkinan lain. Azar Nafisi, dalam buku barunya, The Republic of Imagination (terbit pada 2015), juga mencemaskan perkembangan masyarakat Amerika yang ia sebut mengalami ‘kelambanan intelektual’.
Kecemasan juga diungkapkan oleh Albert Gore, Wakil Presiden AS di masa pemerintahan Bill Clinton. Prinsip-prinsip fundamental kebebasan Amerika, menurut Al Gore dalam The Assault on Reason (2007), telah diselewengkan oleh politik ketakutan, penyalahgunaan kepercayaan, kekuatan budaya media yang semakin terpusat, dan merosotnya proses checks and balances di dunia politik.
Namun Al Gore percaya, demokratisasi informasi dan kekuatan Internet untuk membangun-komunitas dapat memainkan peran penting dalam merestorasi demokrasi yang rasional. Potensi itu memang ada, tapi Al Gore tampaknya agak mengabaikan hasil studi yang menyebutkan bahwa teknologi Internet dan budaya “tunjuk-dan-klik” (point-and-click) telah mereduksi kemauan, dan kemudian kemampuan, orang untuk berpikir mendalam. Orang malas berpikir yang lebih jauh.
Always On: Language in an Online and Mobile World (2008), karya Naomi S. Baron, menunjukkan bagaimana maraknya komunikasi elektronik telah merusak kemampuan siswa untuk menulis prosa—orang enggan untuk berefleksi, tidak sabar lagi dalam menempuh kesukaran untuk menemukan kata-kata dengan diksi kuat untuk mengekspresikan diri. Komunikasi langsung semakin berkurang dan orang menjadi cenderung asyik dengan diri sendiri.
Kebiasaan bekerja serba-cepat yang dipermudah oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan orang cenderung melakukan sejumlah pekerjaan secara serentak (multi-tasking). Instan, bahkan tanpa jeda. Mula-mula orang dipaksa untuk tidak berpikir panjang, apa lagi berefleksi, untuk kemudian paksaan itu merasuk menjadi laku sehari-hari.
Is Google Making Us Stoopid? Begitu tanya Nicholas Barr dalam The Atlantic. Menurut Carr, pemakaian Internet setiap hari membuat otak kita semakin terbiasa membaca sekilas saja dan bukan berkonsentrasi secara berkelanjutan seperti yang dibutuhkan ketika membaca buku, mendengarkan ceramah, dan menulis esei panjang. Dampak paling besar bagi generasi yang sedang tumbuh, kata Carr, terlihat di ruang-ruang kuliah, yakni mereka yang disebut digital natives—generasi yang lahir di era digital.
Politik kuasa dan perkembangan teknologi yang diterima tanpa reserve, dalam konteks ini, menjadi hulu bagi mengalirnya arus sungai yang sama: anti-intelektualisme. Akan tetapi, bisa jadi, kedua aspek itu bukanlah sisi-sisi yang terpisah, melainkan berjalin-berkelindan dengan politik kuasa menjadi hulu utama.
Ketika kekuasaan menekan dan membatasi ruang gerak warga, teknologi komunikasi dan informasi (Internet) menjadi wahana pelarian dari “dunia nyata.” Sikap acuh tak acuh kepada pencarian kebenaran menemukan jalan keluarnya berupa keasyikan di “dunia maya.”
Keprihatinan ini bukan sesuatu yang baru. Kira-kira duapuluh tahun yang silam, Allan Bloom mengungkapkan kekhawatirannya atas anti-intelektualisme dengan secara khusus menyoroti pendidikan tinggi di Amerika. “Komunitas sejati manusia ialah komunitas yang terdiri atas mereka yang mencari kebenaran, mereka yang berkehendak ingin mengetahui… seluruh manusia yang meluaskan hasrat mereka untuk mengetahui,” tulis Bloom dalam The Closing of the American Mind (1987).
Ketika dalam sebuah masyarakat, pencarian kebenaran itu bukan lagi yang utama, masyarakat itu berada dalam kegentingan. Ketidakacuhan kepada kebenaran merupakan ancaman bagi masyarakat terbuka, seperti halnya politik ketakutan menjadi ancaman bagi masyarakat terbuka.
Situasi itulah yang barangkali dimanifestasikan dengan rasa cemas oleh Susan Jacoby dalam The Age of American Unreason. Zaman ketika nalar tertidur, sebuah ancaman yang barangkali tidak kasat mata.
Tanda-tanda itu dapat kita jumpai di sini, di negeri kita, hari-hari ini. (Ilustrasi ‘El sueño de la razon produce monstruos’ karya Francisco Goya (1799), sbr: wikipedia). ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.