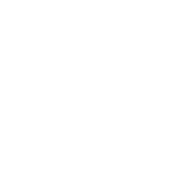Suryana Sudrajat
Pengasuh Balai Pendidikan Pondok Pesantren Darul Ihsan, Anyer
Salah satu kewajiban yang mesti ditunaikan kaum muslim selama Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitrah. Waktu penunaiannya bisa dilakukan pada awal puasa sampai menjelang salat Idul Fitri. Memberikan zakat merupakan refleksi dari rasa syukur. Ia juga merefleksikan sebuah kesadaran bahwa apa yang dimiliki hakikatnya merupakan pemberian Allah yang harus disalurkan kepada mereka yang berhak (mustahik). Dengan demikian, zakat (juga infak dan sedekah) bisa dipandang sebagai cara Sang Khalik untuk membangkitkan kedermawanan dan kebajikan pada makhluk-Nya.
Masifnya gerakan zakat, infak, dan sedekah belakangan ini, selain menandakan betapa banyak orang yang menemukan kebahagiaan melalui ibadah, mengindikasikan kesalehan sosial kaum muslim. Tetapi, agaknya ibadah yang berdimensi sosial itu cenderung dihayati dan dilaksanakan sebagai ritus, lebih berorientasi kepada tazkiyah an-nafs, penyucian diri. Padahal ruh zakat sejatinya merupakan sarana pendidikan dari Tuhan kepada manusia untuk membangun solidaritas dan menegakkan keadilan sosial.
Mengapa ibadah sosial itu tidak bertransformasi menjadi akhlak sosial? Syahdan, salah satu penyebab macetnya transformasi itu terkait dengan faktor budaya, yakni budaya yang bersandar pada nilai-nilai materialisme, egoisme, dan persaingan untuk menguasai hajat hidup. Arief Budiman pernah menyebutnya sebagai budaya MEP. Kekayaan, misalnya, dianggap sebagai ukuran martabat. Orang selalu mempersoalkan what do you have, bukan what are you. Anda bisa seorang yang jujur, yang pandai, tapi orang selalu mengatakan: ya, tapi kok miskin? Tak berarti kejujuran tidak penting. Tapi kaya sekaligus jujur lebih baik. Kalau jujur tapi miskin, sepertinya percuma. Nilai kedua, egoisme, mengedepankan diri sendiri sebagai yang paling utama. Solidaritas tentu boleh, tapi saya yang lebih dulu.
Adapun yang ketiga mengutamakan prinsip "yang kuat yang menang", jika perlu dengan memperlemah orang lain. Kita selalu ingin meningkatkan daya saing, tapi hanya supaya bertambah kaya. Bersaing dalam kejujuran dianggap tidak berguna lantaran hanya sedikit menambah profit. Persaingan bukan hal buruk, tentu. Ungkapan Al-Quran yang populer: fastabiqul khairat, bersainglah dalam hal-hal baik. Lagi pula, tanpa kompetisi, mana mungkin hidup kita bergairah? Hanya, seperti diingatkan Arief Budiman, kalau persaingan itu berkombinasi materialisme dan egoisme, ia bisa menjadi sangat destruktif: menciptakan masyarakat berkelas dan menindas.
Berbagai khotbah, penataran, pidato-pidato, untuk menangkal segi-segi negatif budaya MEP masih berlangsung. Hasilnya seakan muspra, kalau bukan malah menciptakan hipokrisi. Sebab, hanya dalam pelbagai seremoni itulah nilai-nilai nonmaterial, seperti pengorbanan pribadi, solidaritas sosial, dan keadilan muncul. Bukan di lapangan. Juga revolusi mental itu, agaknya.
Aspek-aspek runyam dari budaya MEP memang tidak bisa dikikis habis, tapi bisa dikurangi lewat instrumen demokratisasi. Bahkan Abdurrahman Wahid pernah mengusulkan agar "pemelukan" ide-ide seperti hak asasi, keadilan, dan demokrasi dimasukkan ke faktor keberagamaan. Dengan begitu, meningkatnya gairah keberagamaan, seperti masifnya gerakan zakat, sedekah, dan infak, akan diikuti oleh tegaknya akhlak sosial. Wallahu a'lam.
Ikuti tulisan menarik A Suryana Sudrajat lainnya di sini.