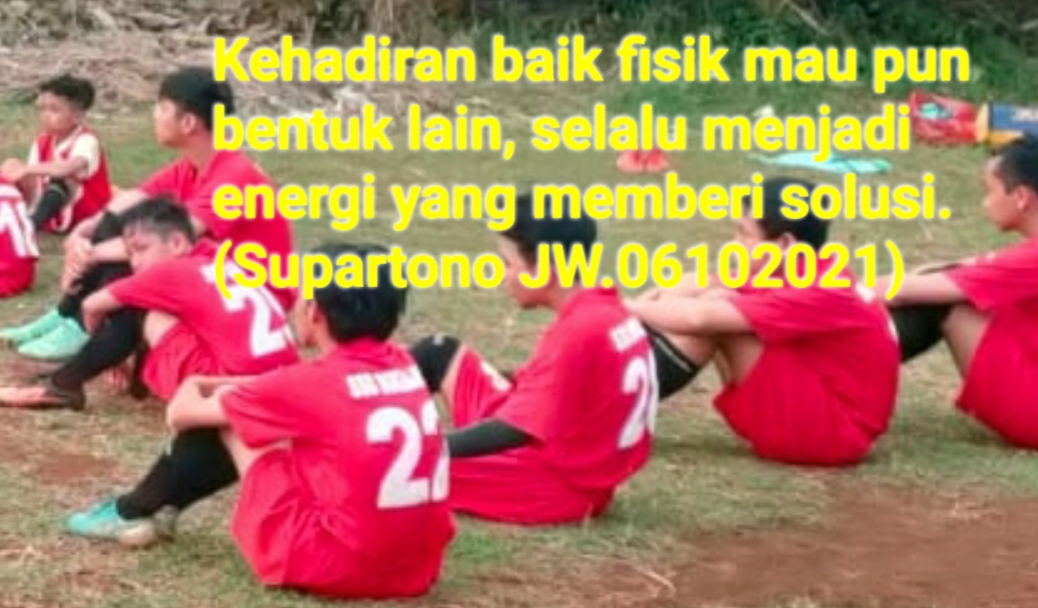Ketika Prancis menjadi tuan rumah Piala Dunia 1998, tim sepak bola nasionalnya yang dijuluki Le Bleus sebenarnya tak diunggulkan. Tapi tim dengan pemain-pemain yang merupakan keturunan Prancis, Afrika, dan Arab ini malah telak menaklukkan Brasil yang lebih dijagokan dan menjadi juara. Prancis bersukacita.
Kemenangan itu membuka kesempatan bagi Prancis untuk percaya bahwa "bersatu dalam perbedaan" bukan semata-mata slogan-bahwa binekanya Prancis justru mengukuhkan negara, bukan melemahkannya. Untuk sesaat, sejalan dengan meruyaknya kebanggaan Prancis terhadap karakter multikulturalnya, warna kebangsaan seolah-olah berubah, dari bleu, blanc, et rouge (biru, putih, dan merah) menjadi black, blanc, et beur (hitam, putih, dan Arab).
Menguatnya optimisme terhadap masa depan satu bangsa Prancis itu bagaikan memperoleh suntikan steroid dua tahun kemudian: tim Le Blues menjuarai Piala Euro.
Yang tak terlihat di balik itu sesungguhnya adalah ketegangan yang sedang meningkat di tengah-tengah masyarakat. Ekonomi ketika itu mandek; kesenjangan sosial yang oleh Jacques Chirac, saat memulai jabatannya sebagai Presiden, dijanjikan hendak direparasi justru kian melebar. Tak berlebihan jika, pada tahun yang sama dengan saat kemenangan Le Blues di Piala Euro, lebih dari sepertiga responden menjawab oui (ya) dalam jajak pendapat yang menanyakan "apakah pemain keturunan asing terlalu banyak dalam tim".
Kalaupun bukan kebencian, ada nada iri di balik jawaban itu. Hal ini menegaskan kenyataan betapa, bagaimanapun, bahkan hingga kini, Prancis belum juga sanggup menerima kenyataan sebagai sebuah melting pot, wilayah yang membaurkan manusia dari berbagai asal usul. Banyak orang yang masih meyakini mitos bahwa Prancis itu homogen; sebagian dari mereka bahkan rasialis. Padahal jumlah orang asing terus meningkat. Pada 1886 baru ada sejuta orang asing di antara 40 juta penduduk. Tapi sejak orang-orang Afrika Utara mulai berdatangan pada 1910, jumlah orang asing terus berlipat ganda. Pada akhir 1930 arus masuk imigran ke Prancis jauh lebih tinggi ketimbang ke Amerika Serikat.
Tantangan untuk meruntuhkan mitos itu kini kian menjulang. Dibandingkan dengan masa ketika Le Blues berjaya itu, situasinya lebih genting. Setelah terjadi serbuan terorisme di kantor koran Charlie Hebdo dan kemudian serangan serupa secara serentak di sejumlah lokasi di Prancis, kaum kanan bertambah leluasa mengatrol popularitasnya. Mereka menggoreng-goreng sentimen anti-imigran dan terus menambah pendukung. Dan kecenderungan serupa terjadi di seluruh penjuru Eropa.
Kejayaan Le Blues seperti 16-18 tahun lalu bisa jadi setengah mati diperlukan saat ini, demi sebuah persatuan, atau setidaknya sebagai pelipur lara sementara. Tapi, dengan komposisi tim yang sulit dibilang lagi sebagai bleu, blanc, et rouge, kalaupun memang gelar juara direbut lagi, tampaknya pesta bersamanya bakal berlangsung sebentar saja-seperti mimpi yang datang ketika seseorang baru bisa memejamkan mata menjelang fajar.
*) Diedit sedikit, tulisan ini sebelumnya diterbitkan di Koran Tempo edisi 30 Juni 2016.
Ikuti tulisan menarik purwanto setiadi lainnya di sini.