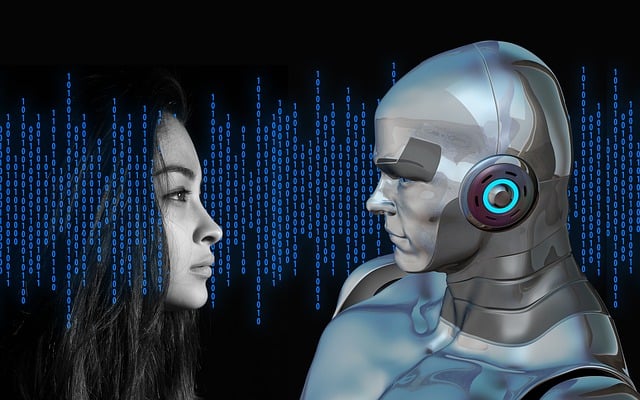Belum hilang keterkejutan kita tentang adanya temuan tentang pembagian KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang menumpuk di kelurahan, kembali publik disodori kelebihan pagu tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp.23,4 trilyun ditengah krisis fiskal yang harus diatasi dengan tax amnesty yang menyasar kita-kita juga. Artinya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai digenjot untuk memperbesar penerimaan negara, sedangkan Kemdikbud justru sibuk memboroskan anggaran melalui berbagai proyek yang tidak ada kaitannya dengan Nawa Cita No.5 dan Nawa Cita No.8 serta SDGs No.4
Proyek pertama, kekacauan pendistribusian KIP terjadi karena KIP dianggap sebagai “proyek bagi-bagi uang” terbaru yang terlepas kaitannya dengan Education for All (EFA) yang sudah didengungkan UNESCO sejak tahun 1968. Sehingga sebagai proyek baru, semuanya harus dirancang baru yang tidak ada hubungannya dengan upaya peningkatan kualitas SDM kita yang kebanyakan masih berpendidikan SD. Sebagai policy maker, Kemdikbud abai pada kenyataan ini : Jumlah SD : 148.361, jumlah SMP : 36.425, dan jumlah SMA : 10.765, artinya banyak anak yang putus sekolah (drop out) di tingkat SD sehingga angka partisipasi kasar (APK) tidak pernah membaik. Education for All (EFA) bukan merupakan concern Kemdikbud sampai saat ini, artinya program Wajib Belajar 9 tahun itu masih merupakan slogan.
Akibatnya KIP hanya dipandang sebagai proyek pendistribusian kartu, persis seperti cara Kemdikbud mendistribusikan soal-soal Ujian Nasional ke berbagai daerah. Dengan cara memandang diri hanya sebagai task force agen distributor pemerintah, Kemdikbud mengabaikan tujuan utama pembagian kartu ini (mengabaikan dirinya sebagai policy maker yaitu terpenuhinya janji Nawa Cita No.5) sehingga sikut-sikutan proyek dan “cari muka” nampak jelas dari pengabaian akan pengalaman jajarannya sendiri dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan BOP PAUD (Bantuan Biaya Pendidikan Anak Usia Dini) dulu.
Hal ini mudah ditelusur karena KIP 2016 menggunakan data terbaru dari Basis Data Terpadu (BDT) yang diterima bertahap dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) mulai 10 Februari hingga 1 Maret 2016 (bukan menggunakan data dari Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan) yang selalu diperbarui oleh Kemdikbud). Lalu KIP disalurkan melalui PT Satria Antaran Prima Express dan PT Dexter Expresindo (bukan melalui Dinas Pendidikan atau PT Pos Indonesia yang memiliki aparat sampai ke tingkat kelurahan). Akibatnya 10%-20% KIP menumpuk di kelurahan hanya karena tidak tersedianya uang transpor untuk membagi KIP tersebut ke keluarga sasaran. Akibat lanjutannya adalah banyaknya KIP yang tidak tepat sasaran dan salah alamat.
Alasan bahwa sebaran KIP sangat luas karena menjangkau pendidikan formal dan non formal tentu tidak dapat diterima karena Dana Rintisan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan Dana Rintisan Desa Vokasi sudah lama disalurkan Kemdikbud sampai ke tingkat kelurahan.
Belum lagi masalah pencairan dananya yang malah memperpanjang rantai birokrasi karena KIP hanya bisa dicairkan ke bank rekanan setelah memperoleh tanda tangan dan stempel sekolah. Lalu pertanyaannya, kenapa KIP tidak dikirim langsung ke sekolah saja sesuai data Dapodik dari Kemdikbud (tidak ke kelurahan dengan data BDT dari TNP2K) dan kalau menggunakan data BDT, kenapa KIP tidak menyasar anak yang putus sekolah (drop out) atau tidak menyasar anak yang semestinya berhak menerimanya. Dengan demikian, proyek KIP ini justru telah merampas hak anak miskin dan terpinggirkan untuk memperoleh pendidikan lanjut.
Proyek kedua, adalah proyek tunjangan sertifikasi guru yang sejak dulu tidak pernah dikaitkan dengan kinerja guru atau kompetensi guru. Model PGPS (Pinter Goblok Penghasilan Sertifikasi itu sama) dan berapapun nilai UKG (Uji Kompetensi Guru), tunjangan sertifikasi tetap ditebar. Akibatnya Dapodik menjadi mainan baru dari jajaran birokrat Kemdikbud untuk menentukan nasib guru, siapa yang akan mendapat tunjangan sertifikasi dan siapa yang namanya tiba-tiba lenyap dari daftar penerima tunjangan sertifikasi. Semuanya serba misteri.
Oleh sebab itu tidak mengherankan bila besaran dana tunjangan sertifikasi guru juga tidak memperhitungkan banyaknya guru yang pensiun atau mutasi pada tahun anggaran berjalan, dan tidak memperhatikan banyaknya guru di sekolah negeri yang tidak bisa memenuhi kewajiban 24 jam mengajar dan harus memenuhi kekurangan kewajiban jam mengajar itu di sekolah swasta, namun jarang datang mengajar di sekolah swasta yang telah memberi tambahan kekurangan jam mengajar itu. Mereka tetap dapat menikmati tunjangan sertifikasi guru.
Maka sebenarnya agak mengherankan kalau pagu anggaran dana sertifikasi guru itu baru dipotong Rp 23,4 trilyun saat ini, seharusnya dipotong sejak dulu. Lebih mengherankan lagi kalau Mendikbud yang baru, Prof Muhajir Effendi mewacanakan untuk mengurangi kewajiban mengajar 24 jam itu, lalu ukuran pemberian tunjangan sertifikasi guru itu apa? Slogannya bukan lagi PGPS, tetapi RMS (Rajin atau Malas, tunjangan Sertifikasi tetap sama)
Usulan agar tunjangan sertifikasi itu disatukan dengan gaji guru, tentu tidak realistis, karena pemberian tunjangan sertifikasi itu sebenarnya melanggar Pasal 43 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional : “Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi”
Dalam kenyataannya, sertifikasi diberikan setelah dinyatakan lulus dalam Diklat Kemdikbud selama 3 hari, bukan diberikan oleh IKIP atau Universitas yang mempunyai FKIP yang terakreditasi.
Pemberian tunjangan sertifikasi sebagai program tebar uang itu juga melanggar Pasal 61 ayat 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional : “Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi”
Artinya, guru-guru yang mendapat nilai UKG (Uji Kompetensi Guru) di bawah standar (jumlahnya banyak sekali), menurut UU, seharusnya dicabut tunjangan sertifikasinya. Kenyataannya, meskipun nilai rerata UKG secara nasional hanya 56,69 (dibawah batas minimal yaitu 75,0) namun tunjangan sertifikasi guru terus ditebar.
Masalahnya, guru-guru yang berkualitas menumpuk di daerah tertentu, karena memang Kemdikbud selalu membangun sekolah-sekolah negeri baru di dekat sekolah-sekolah swasta yang mandiri (sekolah swasta gaji gurunya tidak merepotkan pemerintah), bukan mendirikan sekolah negeri di daerah yang belum terlayani atau terjangkau pendidikan berkualitas.
Dengan demikian, banyak sekolah swasta yang mati (sekolah Muhammadiyah, sekolah Taman Siswa, sekolah PGRI, sekolah Bhayangkari (milik POLRI) dan sekolah Persit Kartika Candra Kirana (milik TNI AD) satu persatu ditutup karena muridnya tersedot ke sekolah negeri di dekatnya. Kisah buku dan film Laskar Pelangi itu adalah potret sekolah Muhammadiyah yang dibiarkan merana oleh Kemdikbud.
Proyek “mematikan” sekolah swasta ini secara sengaja dan sistematis dimulai ketika Kemdikbud menutup Direktorat Sekolah Swasta di Kemdikbud dan mulai ekstensif mendirikan sekolah negeri dimana-mana, lupa akan kegagalan pendirian SD Inpres dimana-mana pada jaman Soeharto.
Pendidikan bukan soal membangun gedung, tetapi membangun SDM termasuk menyediakan guru yang kompeten. Hanya dengan kualitas guru yang baik maka tujuan peningkatan kualitas SDM sebagaimana diamanatkan dalam Nawa Cita No.5 dan SDGs No.4 akan lebih mudah tercapai (bukan dengan membangun gedung sekolah).
Maka jangan heran kalau banyak kabupaten yang tidak mempunyai sekolah swasta tetapi nilai UKG-nya jauh di bawah standar, menjadikan kabupaten itu bingung sendiri, ketika terjadi pemotongan pagu anggaran tunjangan sertifikasi guru.
Banyaknya anak jalanan (street children) dan anak-anak yang menganggur di usia muda memerlukan partisipasi publik dalam pendidikan. Masih ingat kasus Yuyun yang diperkosa 14 remaja putus sekolah dan pengangguran sampai meninggal di Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu ? Seandainya Dinas Pendidikan Kabupaten Rejanglebong dan Dinas-dinas Pendidikan Kabupaten lain mempermudah perijinan pendirian sekolah swasta, maka anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri ini dapat dididik di sekolah swasta. Tapi dimana-mana, partisipasi publik yang justru digalakkan di sektor ekonomi justru diabaikan di sektor pendidikan.
Anehnya, masalah menumpuknya guru-guru berkualitas di daerah-daerah tertentu dan tidak tertampungnya anak-anak miskin di sekolah-sekolah negeri itu tidak diatasi dengan peningkatan partisipasi publik dalam pendidikan, tapi diatasi melalui pelatihan guru (lagi), lalu untuk apa program diklat sertifikasi guru yang sudah menelan anggaran sangat besar itu?
Lihatlah pernyataan Ketua Ikatan Guru Indonesia : “Karena itu kami berupaya melaksanakan pelatihan di seluruh Indonesia. Setiap minggu ada 30-50 pelatihan guru di 30-50 kabupaten/kota. Kami kawatir suatu ketika tunjangan guru dicabut karena tidak banyak meningkatkan kompetensi guru ”, ujar Muhammad Ramli Rahim. (Kompas, Selasa 30 Agustus 2016 halaman 13 : “Perbaikan Kualitas Pembelajaran Belum Tersentuh”)
Aneh sekali, kegagalan suatu diklat pelatihan guru diatasi dengan proyek pelatihan guru lagi, bukan menelusur kualitas materi pelatihan guru tersebut dan siapa penyusunnya.
Misalnya “pembodohan guru by design” : empat Kompetensi Inti yang selama ini dipraktekkan (sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan) ternyata tidak mengacu pada ketentuan internasional sehingga tidak terukur (rapor berkali-kali berganti). Empat Kompetensi Inti itu ternyata tidak mengacu pada “Empat Kerangka Dasar dan Karakter” dari SEIP Intelligence, sehingga Kompetensi Inti 1 (sikap spiritual) tidak bisa diukur dengan SQ (Spiritual Quotient).
Begitu juga empat Kompetensi Inti itu ternyata tidak mengacu pada Core Skills dari 21st Century Learning karena Core Skills itu berjumlah enam (bukan empat) yaitu : “berpikir kritis dan solutif”, “kreatif dan imajinatif”, “kolaborasi dan komunikasi”, “menjadi warga negara yang baik”, “literasi digital”, dan “kemampuan memimpin”
Akibatnya, Kompetensi Inti 2 (sikap sosial) tidak mengacu pada Core Skills yang keempat : “menjadi warga negara yang baik” sehingga tidak bisa diukur dengan CQ (Civic Quotient).
Tetapi Kompetensi Inti 1 dan Kompetensi Inti 2 itu diukur melalui pengamatan (observasi) guru yang sudah tentu sifatnya sangat subyektif (bukan lagi penilaian otentik karena dasarnya observasi guru).
Dengan demikian, penilaian Kompetensi Inti 1 (sikap spiritual) dan Kompetensi Inti 2 (sikap sosial) dalam Revisi Kurikulum 2013 itu justru bertentangan dengan dasar hukumnya sendiri yaitu Lampiran Bab V Permendikbud No.22 Tahun 2016 yang menekankan penilaian otentik, dan isi Bab IV Pasal 5 ayat b Permendikbud No.23 Tahun 2016 : “prinsip penilaian obyektif, tidak dipengaruhi subyektivitas penilai”. Dari pelatihan Revisi Kurikulum 2013 itu, nampak jelas bahwa guru dibuat bodoh by design, demi mengejar penyerapan anggaran melalui proyek.
Maka pendidikan tidak akan maju tanpa peran serta dan partisipasi masyarakat dengan mendirikan sekolah swasta yang mandiri. Sumber daya Kemdikbud tidak akan cukup untuk mewujudkan Nawa Cita No.5 dan SDGs No.4
Proyek ketiga adalah proyek abadi Kemdikbud, yaitu proyek UN (Ujian Nasional). Padahal kredibilitas penyelenggaraan Ujian Nasional selalu dipertanyakan, sejak adanya putusan inckracht (putusan kasasi yang final dan mengikat) Mahkamah Agung (MA) No. 2596 K/PDT/2008 yang meminta pemerintah membatalkan Ujian Nasional sampai sarana dan prasarana sekolah terpenuhi dan kompetensi guru ditingkatkan.
Apalagi sejak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan aanmaning (teguran) kepada Mendikbud M. Nuh karena dianggap melalaikan putusan final kasasi MA terkait Ujian Nasional. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil Mendikbud untuk mendengarkan aanmaning pada hari Rabu tanggal 10 April 2012, namun Mendikbud M. Nuh tetap bersikukuh untuk menyelenggarakan Ujian Nasional. Mendikbud Anies Baswedan yang diharapkan akan memenuhi putusan MA di atas, ternyata terjebak dalam proyek pelestarian Ujian Nasional.
Hal ini berlanjut ke Ujian Nasional SD yang sebenarnya sudah dihapus sejak jaman Mendikbud M.Nuh, karena penghapusan UN SD itu telah diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 1 PP No.32 Tahun 2013 dan penghapusan Ujian Persamaan SD (Paket A) telah diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 2 PP No.32 Tahun 2013, namun anehnya Ujian Nasional SD ini dihidupkan kembali oleh Mendikbud Anies Baswedan dengan “baju baru” yaitu Ujian Utama SD. Nampak bahwa jajaran Kemdikbud mulai melupakan arti dari Wajib Belajar 9 tahun dan lalai bahwa penyelenggaraan Ujian Utama SD itu justru akan memperkecil APK (angka partisipasi kasar) pendidikan lanjutan.
Hendaknya Kemenkeu jauh-jauh hari sudah mencoret penganggaran proyek UN ini dan mengalihkannya untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dengan spesifikasi yang ketat supaya tidak terjadi mark up.
Proyek keempat adalah proyek Literasi Sekolah. Pembudayaan literasi sebenarnya wajib dilaksanakan dalam Kurikulum 2006 karena diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 PP No.19 Tahun 2005 : “Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis”, yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 PP No.19 Tahun 2005 : “Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan”. Dengan demikian, pembudayaan literasi ini merupakan proses pengembangan kemampuan berpikir abstrak yang terintegrasi dalam kurikulum dan terukur, dimana Kompetensi Dasar dan Indikatornya sudah merinci pembuatan ringkasan (resume) dari apa yang dibaca siswa, bahkan memberi ulasan (review) dan timbangan buku (resensi), serta terlatih membuat karya tulis (esai).
Hanya sayangnya kedua pasal penting ini dihapus dalam Kurikulum 2013 (tidak tercantum lagi dalam PP No.32 Tahun 2013), artinya budaya literasi ini sudah tidak tercantum lagi dalam Kompetensi Dasar dan Indikator di Kurikulum 2013 dan revisinya.
Tapi anehnya pada tanggal 18 Agustus 2015, Mendikbud malahan meluncurkan Program Literasi Sekolah : “Bahasa Penumbuh Budi Pekerti” lewat Permendikbud No.23 Tahun 2015. Nafas proyeknya langsung terlihat jelas.
Pertama, Permendikbud itu tidak mempunyai cantolan PP, hingga sukar diintegrasikan dalam Kurikulum 2013 dan revisinya yang sudah terlanjur menghapus budaya literasi (sukar merumuskan kembali Kompetensi Dasar dan Indikator, serta Indikator Keberhasilannya yang sudah terlanjur dihapus itu). Permendikbud itu hanya akan berhenti sebagai program/proyek literasi, tidak akan beranjak ke budaya literasi, karena program ini berdiri di luar kurikulum, terlepas dari konteks kurikulum.
Kedua, program ini hanya mewajibkan siswa membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai (tidak ada cukup waktu untuk merefleksikan bahan bacaan “penumbuh budi pekerti” itu) sehingga kosa kata itu menjadi nir makna. Kemdikbud berkilah, bahwa kewajiban membaca selama 15 menit ini hanya pemancing. Masalahnya, untuk membuat kewajiban membaca ini menjadi budaya literasi diperlukan pengasahan daya imajinasi dan kemampuan mengolah informasi dari buku, yang tidak bisa dicapai bila tidak ada Indikator Keberhasilannya di Kurikulum 2013 dan revisinya. Program ini bisa menjadi proyek yang tidak terkait dengan esensi materi dan internalisasi nilai.
Ketiga, pembagian jutaan buku (bukan e-book) ke sekolah-sekolah dimana guru dan muridnya sudah terbiasa menggunakan gawai, akan menjadikan perpustakaan sebagai gudang buku saja, karena guru dan siswa sudah terbiasa dengan budaya visual, dimana kemampuan berpikir abstrak kurang terlatih, hingga agak sukar mencerna teks-teks panjang di buku-buku agak tebal tanpa visualisasi obyek.
Oleh sebab itu, diperlukan “jembatan” untuk mengatasi “gap” ini, yaitu menjembatani antara pola pikir linier (satu dimensi imaji) dan pola pikir abstrak (tiga dimensi rekontruksi). Jembatan itu adalah menggambar prespektif dan proyeksi yang adanya justru di Kurikulum 1975, dimana sains dan matematika masih diajarkan sebagai art, bukan sekedar pengetahuan saja, dimana siswa dilatih menemukan metafisika dalam fisika, poesi dalam matematika, hasrat dalam sejarah, filosofi dalam administrasi politik dan ekonomi, ketuhanan dalam penalaran, melodi dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari.
Oleh sebab itu, di Kurikulum 1975 masih dimungkinkan untuk belajar Ilmu Bumi Falak (astronomi), Ilmu Ukur Melukis (BM), dll Sebenarnya, Kurikulum 2006 sudah merevitalisasi Kurikulum 1975 melalui analisis kurikulum dan analisis esensi materi, hanya sayangnya semuanya dihapus dalam Kurikulum 2013.
Menakar tiga masalah di atas, tentu lebih masuk akal dan lebih hemat anggaran bila Kemdikbud kembali menerapkan Kurikulum 2006 yang sudah mengimplementasikan budaya literasi secara terstruktur (bukan sekedar program literasi yang keberlanjutannya sangat tergantung pada alokasi dana proyek).
Maka agak aneh kalau Mendikbud Anies Baswedan pada pernyataannya tanggal 30 Desember 2015 lalu, menegaskan bahwa Kemdikbud tidak akan menggunakan Kurikulum 2006, lupa pada Surat Edaran Mendikbud No. 179342/MPK/KR/2014 yang ditanda tangani oleh Mendikbud Anies Baswedan sendiri tanggal 5 Desember 2014, tentang dimungkinkannya sekolah untuk menerapkan kembali Kurikulum 2006. Rupanya yang dimaksud adalah meneruskan kembali berbagai proyek (baru).
Dengan begitu, Program Literasi Sekolah ini adalah program ekliktik, hanya tempelan pada Kurikulum 2013 dan revisinya. Hal ini nampak dari digelarnya pelatihan guru untuk program literasi sekolah yang terpisah dari pelatihan 761 instruktur nasional Revisi Kurikulum 2013, padahal pelatihan instruktur nasional ini baru dilaksanakan tanggal 20-24 Maret 2016 (7 bulan setelah pencanangan Program Literasi Sekolah). Program ini belum juga disinkronkan dengan Kegiatan Belajar dan Indikator Keberhasilan di Silabus Revisi Kurikulum 2013 hingga tidak termaktub dalam penilaian seturut Permendikbud No.53 Tahun 2015. Oleh sebab itu, agak sukar mengaitkan program ini dengan upaya peningkatan kulaitas pendidikan, seperti yang dituntut dalam Nawa Cita No.5 dan SDGs No.4
Proyek kelima adalah “Program Guru Pembelajar”. Proyek ini merupakan duplikasi dari Indonesia Digital Learning yang diselenggarakan oleh PT Telkom dan tidak sinkron dengan Proyek “Palapa Ring” : “menuju masyarakat informasi Indonesia” yang sudah diluncurkan oleh Kominfo karena Kemdikbud justru menghapus mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di era digital ini pada semua jenjang pendidikan.
Program Guru Pembelajar ini tetap menjadikan guru sebagai konsumen berbagai web terpilih, bukan menjadikan guru sebagai pembelajar seumur hidup (a lifelong learner). Karena Kemdikbud tidak kunjung mengintrodusir Core Skills yang kelima dari “21st Century Learning” yaitu “literasi digital”, malah memberlakukan Kompetensi Inti (KI) yang tidak terkait dengan TIK dan Prakarya yang mencakup pembuatan animasi (pengolahan gambar tangan menjadi gambar bergerak) di semua jenjang pendidikan, hingga Kurikulum 2013 dan revisinya tidak bersesuaian dengan salah satu topik yang dibicarakan dalam Pertemuan Tahun ke-6 SEAMEO yaitu “digital school” yang sangat memerlukan pengetrapan literasi digital.
Dilain pihak, literasi digital sangat membutuhkan pembelajaran mandiri, sehingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, dapat diikuti dan diaplikasikan secara tepat guna, agar para guru tidak gagap teknologi pada era aplikasi online ini.
Untuk itu diperlukan pengembangan kemampuan untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu (bersikap kritis), lalu melakukan evaluasi dan merefleksikan apa yang sudah dipelajari (menyaring, memilah dan memilih informasi/data primer dan memisahkannya dari informasi pendukung/data sekunder).
Sayangnya upaya untuk berpikir kritis (critical thinking) ini dicerabut dalam Kurikulum 2013 melalui pengabaian relevansi kurikulum terhadap kebutuhan lokal, nasional dan global sebagaimana diusung dalam Pasal 38 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) yang dijabarkan dalam Pasal 60 ayat i PP No.19 Tahun 2005. Melalui semangat link and match inilah dapat ditumbuh kembangkan pembelajaran seumur hidup (a lifelong learning).
Seandainya Program Guru Pembelajar ini diintegrasikan dengan Indonesia Digital Learning dari PT Telkom, maka disamping Kemdikbud dapat menghemat anggaran, Kemdikbud juga terhindar dari memfungsikan diri sebagai inisiator, kreator, impelementor, eksekutor, regulator dan evaluator Kurikulum 2013, yang melanggar prinsip tata kelola yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009, sehingga perubahan dari sekolah regular menjadi sekolah digital sebagaimana diamanatkan dalam pertemuan Forum Tahunan ke-6 SEAMEO di Bandung dapat dimassalkan lebih cepat.
Begitu banyaknya titik kemunduran dalam Kurikulum 2013, karena jajaran birokrat Kemdikbud ngotot ingin melanjutkan proyek keenam yaitu melanjutkan penerapan Kurikulum 2013 karena jajaran birokrat Kemdikbud salah memaknai Pasal 94 b PP No.32 Tahun 2013 dimana tertera “satuan pendidikan wajib menyesuaikan dengan PP ini paling lambat 7 tahun”, yang ditafsir sebagai “semua sekolah wajib menjalankan kurikulum tunggal dan seragam secara nasional, yang dikenal sebagai Kurikulum 2013 paling lambat 7 tahun”.
Padahal ketentuan di atas seharusnya dibaca sebagai wajib menyesuaikan dengan ketentuan dasar hukum (PP-nya) sendiri paling lambat 7 tahun, yaitu menyesuaikan dengan Pasal 77 M ayat 1 PP No.32 Tahun 2013: (pengakuan atas otonomi guru), dan Pasal 77 M ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 (pengakuan atas otonomi sekolah).
Sehingga seharusnya tidak ada kurikulum tunggal dan seragam secara nasional yang bisa menghapus visi dan misi sekolah, yang menyebabkan para guru hanya menjadi robot-robot tukang mengajar, tidak tahu lagi untuk apa dan demi apa dia mengajar, abai akan hak guru untuk menyusun kurikulum dengan standar yang lebih tinggi, sebagaimana digariskan dalam Permendiknas No.24 Tahun 2006. Semuanya menjadi mekanis dan instruksional.
Kesalahan penafsiran ini berlanjut pada pemaknaan Pasal 4 Permendikbud No.160 Tahun 2014 dimana tertera “satuan pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan Kurikulum 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020”, yang ditafsir sebagai “semua sekolah wajib melaksanakan Kurikulum 2013 sebelum tahun pelajaran 2019/2020”.
Padahal pada tahun ajaran 2019/2020 itu kita akan memasuki APEC 2020, sehingga sekolah-sekolah seharusnya sudah menerapkan kurikulum di atas standar baku yang ditetapkan pemerintah (beyond the standard), harus mampu menyusun modul sampai ke tingkat HOT (higher order of thinking) hingga dapat menerapkan SKS murni seperti digariskan dalam Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014 dan tersertifikasi ISO 9001:2008.
Artinya, sebelum tahun 2019/2020, sekolah-sekolah kita harus sudah siap go international, dan hal itu hanya dimungkinkan kalau hak untuk menyusun Silabus dikembalikan kepada para guru seperti yang sudah dipraktekkan dalam Kurikulum 2006.
Maka pada proyek ketujuh yaitu proyek Revisi Kurikulum 2013, Kemdikbud mengeluarkan beberapa kebijakan yang baru, mulai dari pembatasan penerapan Kompetensi Inti 1 (sikap spiritual) dan Kompetensi Inti 2 (sikap sosial), dengan konsekuensi penyederhaan penilaian, sampai ke pemberian keleluasaan sekolah untuk melakukan “pengembangan kurikulum” dan “menjadikan buku-buku teks dari Kemdikbud sebagai buku referensi saja”.
Hal ini akan membuka kembali praktek “main mata” antara penerbit dan Kemdikbud untuk merekomendasikan buku-buku yang akan dipakai di sekolah, dan praktek bisnis perbukuan antara penerbit dan sekolah, yang dulu pernah dilarang karena menyebabkan pendidikan berbiaya tinggi. Kartu Indonesia Pintar atau berbagai program bea siswa yang ada tak akan pernah cukup untuk menutup biaya pembelian buku-buku dari penerbit yang direkomendasikan oleh Pusat Perbukuan dan Kurikulum Kemdikbud.
Maka hendaknya Kemdikbud kembali ke visi pemerintah Jokowi-JK yaitu “pemerintah akan menata ulang kurikulum pendidikan nasional demi keberhasilan revolusi mental”, bukan sekedar melakukan revisi kurikulum, tetapi melakukan “inovasi pembelajaran dan konten”, sebagaimana dibicarakan dalam pertemuan SEAMEO di Bandung itu.
Maka dalam inovasi pembelajaran dan konten, jauh lebih baik kalau kita mengacu pada filsafat perenialisme, mempertahankan yang sudah baik sebagai basic knowledge, lalu tinggal menambah bahan-bahan yang sesuai dengan perkembangan jaman.
Inilah arti hakiki dari pengembangan Silabus. Sebab bila guru mampu menyusun Silabus, maka guru dapat membuat diktat dan modul sendiri hingga memudahkan sekolah menerapkan SKS murni, sesuai tuntutan Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014. Modul ini berisi bahan-bahan dari Kurikulum 1975 dimana sains dan matematika dipahami sebagai art, bukan sekedar pengetahuan. Dimana siswa dilatih menemukan metafisika dalam fisika, poesi dalam matematika, hasrat dalam sejarah, filosofi dalam administrasi politik dan ekonomi, ketuhanan dalam penalaran, melodi dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari.
Kurikulum 1975 dimana anak-anak masih mengenal Ilmu Bumi Falak (astronomi), Ilmu Ukur Ruang (stereometri), Ilmu Pesawat (Mekanika), Sejarah Dunia, dll tanpa menjadikannya sebagai beban belajar. Karena Kurikulum 1975 ini masih mengembangkan 6 wilayah makna yaitu simbolika, empirika, estetika, sinnoetika, etika dan sinoptis.
Inilah yang dimaksud dengan “penataan ulang kurikulum pendidikan nasional”. Aplikasi Nawa Cita No.8 ini adalah kembali ke Kurikulum 2006 agar guru dapat membuat Silabus sendiri dengan konten kurikulum 1975. Melalui otonomi guru ini, guru dapat menambah beberapa bahan yang sesuai dengan perkembangan jaman, tetapi dengan basic knowledge yang kokoh.
Kemudian para guru dapat mendisain kurikulum secara digital agar dapat tersertifikasi ISO 9001:2008. Dengan demikian, para guru dapat menyusun diktat dan modul sampai ke tingkat Higher Order of Thinking, lalu maju ke penerapan SKS (bukan paket SKS), sehingga penerapan e-learning berbasis multiple intelligence dan sekolah digital berbasis keunggulan lokal dapat diakselerasi.
Hentikan proyek-proyek penyerapan anggaran agar ijazah anak-anak kita dapat diakui di luar negeri dalam era globalisasi ini. Jangan biarkan anak-anak kita menempuh kelas foundation, tapi hendaknya mengacu pada sekolah-sekolah swasta yang nekad menerapkan Kurikulum 2006 hingga siswanya dapat langsung mengikuti kuliah di luar negeri tanpa mengikuti kelas foundation.
Penulis adalah pemenang Indonesia MDGs Award 2011
Ikuti tulisan menarik Wendie Razif Soetikno lainnya di sini.