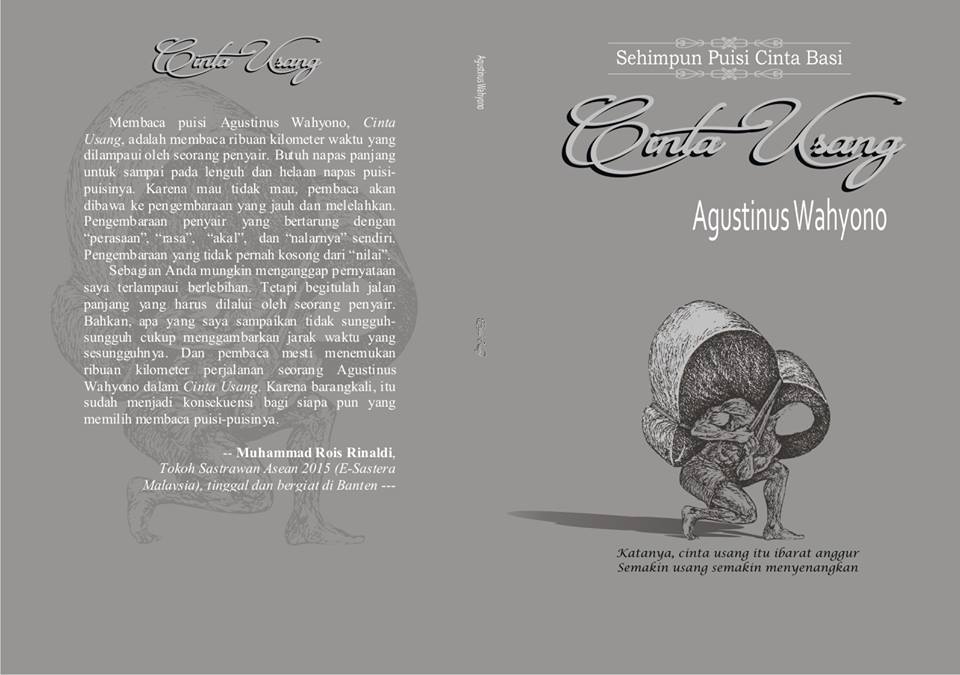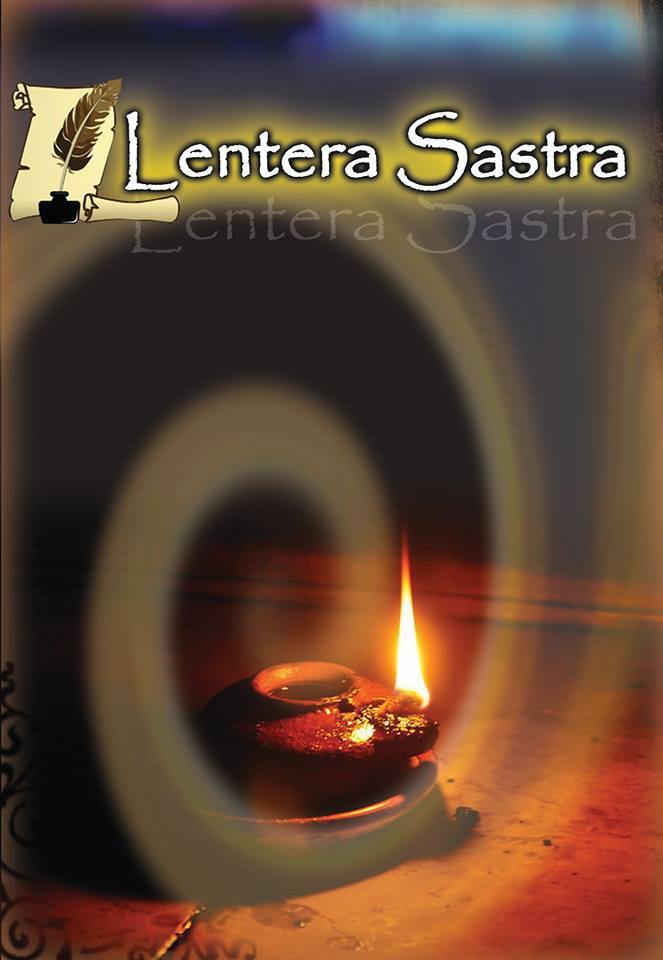Oleh, Muhammad Rois Rinaldi
Membaca puisi Gus Noy, Cinta Usang, adalah membaca ribuan kilo meter waktu yang dilampaui oleh seorang penyair. Butuh napas panjang untuk sampai pada lenguh dan helaan napas puisi-puisinya. Karena mau tidak mau, pembaca akan dibawa ke pengembaraan yang jauh dan melelahkan. Pengembaraan penyair yang bertarung dengan “perasaan”, “rasa”, “akal”, dan “nalarnya” sendiri. Pengembaraan yang tidak pernah kosong dari “nilai”. Sebagian Anda mungkin menganggap pernyataan saya terlampaui berlebihan. Tetapi begitulah jalan panjang yang harus dilalui oleh seorang penyair. Bahkan, apa yang saya sampaikan tidak sungguh-sungguh cukup menggambarkan jarak waktu yang sesungguhnya . Dan pembaca mesti menemukan ribuan kilo meter perjalanan seorang Gus Noy di dalam Cinta Usang. Karena barangkali, itu sudah menjadi konsekuensi bagi siapapun yang memilih membaca puisi-puisinya.
Ia yang telah dengan sadar memosisikan cinta sebagai “yang usang” sekaligus sebagai “yang tidak pernah lekang”; yang menawan dan yang memerdekakan; yang meng-ada-kan dan yang meniadakan; yang menjemukan dan yang menggemaskan; yang berselisih dan yang berpelukan. Ia yang “menerjemah metafora semiotika dari kata sunyi kata bunyi bersilang-selisih bertumpang-tindih bersama sejuta tanya tanpa tadah jawab.”. Membiarkan “Bebintang menggantung di angkasa kata/… mengapung tanpa jeda”. Meski akhirnya ia menjebak pembaca dengan pernyataan, “Sajak memang sekadar singgah pada/Lintasan lampu minyak”. Rentetan dialektika yang menarik untuk terus ditelusuri pembaca. Sebagaimana puisi berikut ini.
Suaramu
Sedepa jalan jarum arloji menjumpa
Sapa dari pancar rekah bibir bungamu
Lebih semerbak daripada sedap malam
Jarum jam arloji terhenti di pinggir
Pertigaan terhadang sekuntum senyum
Ranum terampas roda mesin meraung
*******
“Suaramu” adalah puisi yang mempertemukan dimensi ruang dan dimensi waktu (baca: Teori Relativitas Khusus Einstein). Kata “sedepa” dan “arloji” merupakan kata kunci untuk memahami pertemuan empat dimensi itu. Di dalamnya ada sebuah pertemuan yang cukup sulit dijejak mengapa dan bagaimana. Sehingga pembaca harus menggambarkan sendiri gambaran-gambaran pertemuan di dalam “Suaramu”. Dalam hal ini, penyair tidak sedang menyesatkan pembaca tanpa peta. Pembaca telah diberikan kuncinya dengan gambaran-gambaran abstrak: “Sapa dari pancar rekah bibir bungamu/Lebih semerbak daripada sedap malam”. Pemaknaannya dengan mengurai “tanda” yang tervisualkan dan “Acuan tanda” atau objek yang dijadikan sebagai aspek pemaknaan tanda.
Pada bait pertama (juga pada bait kedua) yang perlu diperhatikan benar, di puisi ini adalah “jarum jam arloji”. “Jarum jam arloji” dapat berarti sebagai waktu yang melingkupi manusia. Artinya, waktu yang menjadi penentu pergerakan dan batas-batasnya bagi manusia. Ini mengingatkan saya pada “Eskatologi”, di mana dalam tradisi-tradisi mistis dikaitkan dengan kelepasan dari “penjara realitas” yang ada, bahkan sebagian agama meyakini adanya penghancuran tempat hidup manusia sebelum sampai pada tempat kehidupan yang berikutnya. Atau “Jarum jam arloji” diposisikan sebagai “yang hidup”, semisal manusia. Di mana ianya tidak diposisikan sebagai waktu, melainkan sebagai yang di dalam lingkup dimensi waktu. Pada posisi ini, pemaknaan akan bergeser menjadi kisah-kisah manusia mengenai pertemuan seusai perpisahan.
Pada bait kedua, “pertigaan”, “sekuntum bunga”, “ranum (yang) terampas”, dan “roda mesin” adalah rentetan simbol yang dihadirkan untuk membangun kisah sekaligus menciptakan tikaian demi tikaian di dalam puisi. Dimana perjumpaan di bait pertama kemudian terenggut begitu saja. Nuansa mengharukan pada bait pertama berubah menjadi sebuah elegi di bait kedua. Sebagaimana kisah-kisah pertemuan yang terlampau ringkas. Pertemuan yang meninggalkan kesan mendalam lantaran perpisahan yang terlampau cepat, bahkan sebelum pertemuan itu benar-benar dapat dimaknai isinya. Di sinilah saya menemukan kesengajaan penyair untuk membuat pembaca bertanya: ini pertemuan macam apa dan perpisahan macama apa dan mengapa pertemuan ini harus ada? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan muncul beribu penafsiran, tergantung pengalaman empiris pembacanya.
Dalam kaitannya, saya rasa perlu membantu pembaca menemukan kunci pemaknaan yang lain. Mari mengajukan satu pertanyaan: mengapa judulnya “Suaramu”? Bukan tubuh, bukan bibir, bukan senyum, bukan langkah, bukan hal-hal fisik lainnya yang menunjukkan ada visualisasi pertemuan. Perhatikan larik pertama dan kedua pada bait pembuka: “Sedepa jalan jarum arloji menjumpa/Sapa …”. Jadi, sesungguhnya ini bukan pertemuan fisik? Lebih logisnya demikian. Perhatikan larik terakhir di bait penutup ini: “Ranum terampas roda mesin meraung”. Yang dirampas adalah suara yang merampas juga suara (baca: raungan roda mesin dalam pengertian sebenarnya atau bukan sebenarnya).
Pada puisi lainnya, penyair yang juga seorang arsitek ini menghadirkan puisi dengan judul “Drawing”.
Merah berbalut hitam mengetuk
Pintu pagi berselimut pesing
Tanpa aba-aba prenjak kupu
Pada ambang pintu pagi berbentang
Gambar berarsir muka sebuah kabar
Merengkuh grogi gigiti kata
*******
Sebagaimana kegiatan Drawing (menggambar), yang membentuk imaji dalam bentuk yang lebih konkret di alat gambar semisal kertas atau kanvas, Gus Noy mendominasi puisi ini dengan imaji visual. Meski imaji visual digunakan kebanyakan penyair untuk membuat puisi lebih jelas dan tegas arah maksudnya, Gus Noy kembali membuat abstraksi. “Merah berbalut hitam” yang “mengetuk pintu” ini tidak dijelaskan apa atau siapanya. Atau ianya memang hadir sebagai “Merah” itu sendiri. Sebagai warna yang dipandang dari kacamata seorang penyair yang juga menggeluti seni rupa yang kesehariannya berprofesi sebagai seorang arsitek. Saya rasa kemungkinan ini cukup logis. Warna memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan manusia. Tidak sekadar warna. Misalnya merah yang kerap dikaitkan dengan keberanian dan kemarahan jika dilihat sebagai simbol universal. Atau jika warna sudah menjadi simbol personal, merah adalah luka, penderitaan, kesukaran, dan lain sebagainya.
Bagaimana bisa “Merah” yang warna mengentuk pintu? Dalam permajasan, kita mengenal personifikasi: majas yang memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati. Tetapi saya rasa penyair ini tidak menghendaki personifikasi untuk merah menjadi simbol yang hidup dalam pengertian yang sebenarnya. Merah adalah warna yang mengetuk pintu imaji yang membuat prenjak kupu terbentang pada ambng pintu pagi yang pesing, secara tiba-tiba. Jadi, mengetuk di sini bukanlah kegiatan mengetuk pintu sebagaimana manusia dan pintu yang diketuk bukan pintu rumah atau pintu pos kamling. Mengetuk dapat diartikan mendorong seseorang untuk melakukan atau merasakan sesuatu lantaran melihat warna merah. Seseorang? Bukankah dalam puisi ini tidak ada tokoh lain selain merah? Dalam puisi ini ada “aku lirik”, orang yang melihat warna merah dan menuturkan kejadian atau gambaran demi gambaran dalam puisi. Dan merah di sini, meski tidak dikenakan majas personifikasi, dapat juga tidak sebagaimana warna pada kain atau tembok, melainkan warna pada rasa dan perasaan manusia.
Di sinilah kemungkinan pemaknaan semakin terbuka luas. Proses pemaknaan semakin asyik dan luas pada dua larik terakhir, penutup yang benar-benar bertenaga: “Gambar berarsir muka sebuah kabar /Merengkuh grogi gigiti kata”. Ada tiga kemungkinan. Pertama, gambar muka adalah gambar yang diarsir oleh “aku lirik” lantaran dorongan warna merah; dan kedua, merah itu adalah warna yang ada pada arsiran muka, warna yang tampak dengan tatapan “rasa” dan “perasaan”. Tentu saja ada kemungkinan lain di luar dua kemungkinan yang saya tangkap. Dan yang perlu diperhatikan betul seusai memilih satu di antara sekian kemungkinan makna, perhatikan dengan sungguh-sungguh satu larik terakhir ini: “grogi grogoti kata”. Apa maksudnya?
Begitulah kiranya sebuah proses pemaknaan puisi. Tidak ada makna pasti. Karena puisi adalah kehidupan yang ditransformasikan dalam bentuk teks. Kehidupan di dalam teks ditentukan oleh pembacanya. Inilah mengapa kerap sekali orang mengatakan bahwa ketika puisi sudah dipublikasikan, penyair mati. Maksudnya, pemaknaan tidak boleh diarahkan oleh penyair. Pemaknaan pembaca harus dibebaskan dengan riang gembira. dan barangkali ada benarnya apa yang dikatakan Riffaterre, memahami puisi itu seperti sebuah donat. Sesuatu yang hadir secara tekstual adalah daging donatnya. Sedangkan sesuatu yang tidak hadir secara tekstual adalah ruang kosong berbentuk bundar yang berada di tengahnya dan sekaligus menopang dan membentuk daging donat menjadi donat.
Sebagai penutup, saya hadirkan satu puisi dari kumpulan puisi Nyanyian Usang karya Gus Noy yang bentuk teksnya sangat pendek, tapi pemaknaannya sangat panjang. Selamat mengembara!
Kecupan Nista
Ada sebuah kecupan
Seperti bibir Yudas Iskariot
Di Taman Getsemani
*******
Banten, 2016
Ikuti tulisan menarik Lentera Sastra lainnya di sini.