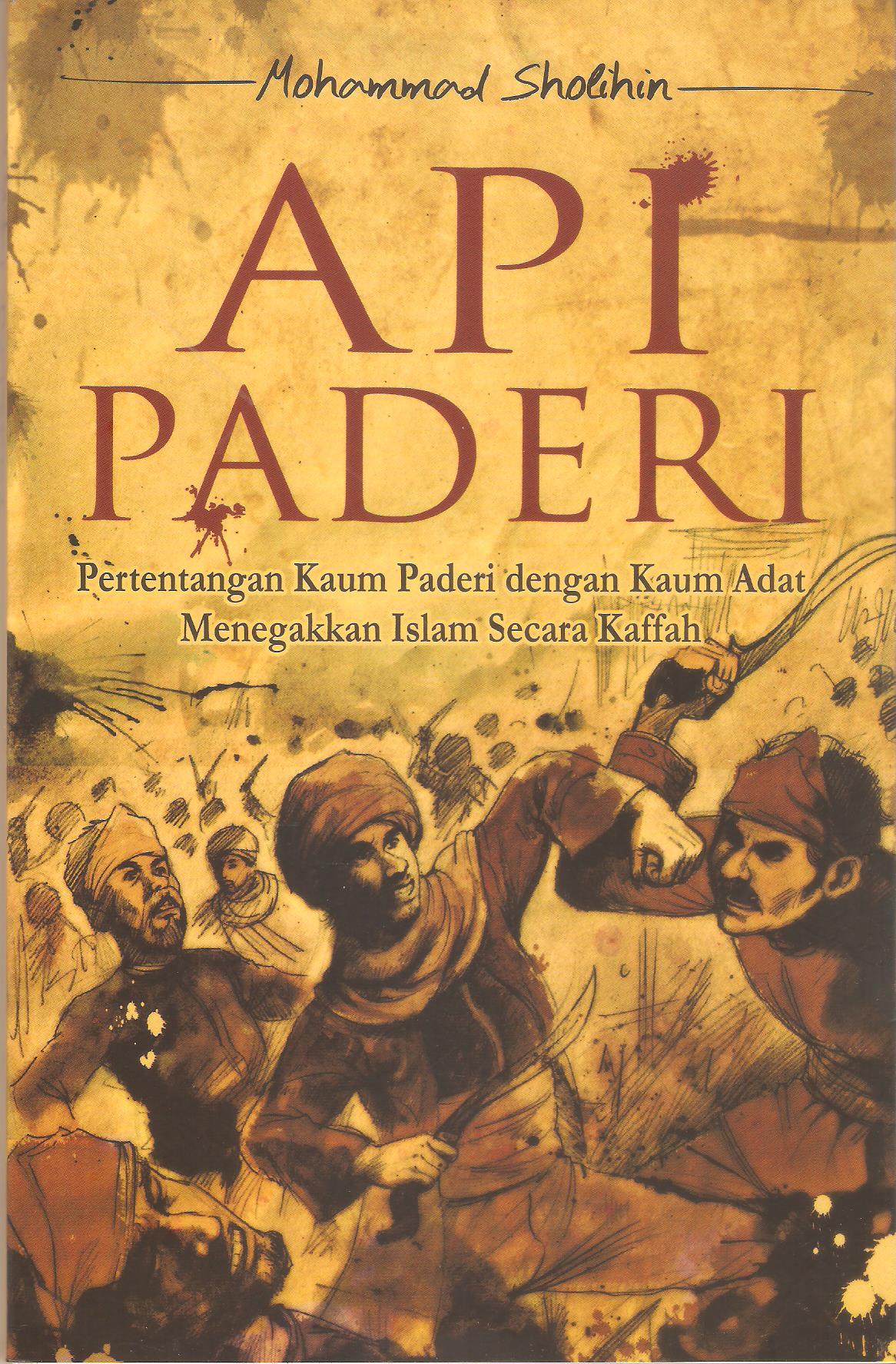Judul: Api Paderi – Pertentangan Kaum Paderi dengan Kaum Adat Menegakkan Islam Secara Kaffah
Penulis: Mohammad Sholihin
Tahun Terbit: 2010
Penerbit: Narasi
Tebal: 215
ISBN: 978-979-168-228-2
Kegundahan melanda saat seseorang atau sebuah gerakan yang selama ini kita yakini adalah pahlawan, ternyata memiliki kisah kelam. Demikianlah yang dialami oleh Muhammad Sholihin (MS), si penulis novel ini, saat mengetahui bahwa gerakan Paderi di Sumatra Barat ternyata pernah berseteru dengan kaum adat. Gerakan Kaum Paderi yang selama ini dikenalnya sebagai gerakan melawan kolonialisme Belanda, ternyata pernah memusuhi kaum adat karena semangat memurnikan ajaran agama. Kegelisahan tersebutlah yang kemudian mendorong MS menulis novel ini. Ia mencoba untuk “membingkai kusut masa gerakan Paderi, yang mampu membuat pedang berdenting, mengairi kanal-kanal dengan air berwarna merah” (hal. 6).
MS memilih Nagari Paninjauan sebagai lokus novelnya. Paninjauan adalah sebuah nagari yang kental dengan adat dan mengalami perjumpaan dengan Islam (shiah) secara damai sekaligus mengalami peperangan ketika kelompok Paderi (Wahabi) memaksa mereka untuk mengikuti aliran yang diyakininya.
Kisah dimulai di arena sabung ayam. Seorang keturunan Arab (Parsi?) bernama Hudzail berhasil mengalahkan ayam aduan milik Datuak Sati yang selama ini tak terkalahkan. Kemenangan dalam adu ayam ini membuat Hudzail mendapat tempat di kampung Paninjauan. Perlahan pati pasti, masyarakat mulai mengikuti keyakinan Hudzail (Islam Shiah). MS mendramatisir proses pengisalam masyarakat Paninjauan melalui sebuah proses debat antara tokoh adat dengan Hudzail. Setelah masyarakat Paninjauan akhirnya menjadi Islam, praktik-praktik ritual Islam diselaraskan dengan budaya lokal. Untuk mendidik masyarakat dalam Islam didirikan masjid dan pesantren. Pesantren ini dipimpin oleh Hudzail dan Midin yang menjadi orang pertama yang tertarik untuk mengikuti ajaran Islam di Paninjauan. Namun ketenangan Paninjauan dirusak oleh datangnya orang-orang Paderi yang beraliran wahabi. Orang-orang Paderi ini melakukan pemurnian ajaran Islam dengan cara pedang. Jika para penganut Islam tidak mau meninggalkan hal-hal yang dianggap menyimpang dan mau mengikuti ajaran wahabi, maka pedanglah yang teracung untuk membunuhnya. Darah orang yang menolak ajaran wahabi adalah halal untuk ditumpahkan. Bhawa semua kibiasaan yang tidak dihalalkan Quran harus dihapuskan dan siapa yang tidak setuju harus dibunuh (hal. 198).
Seperti telah saya singgung di atas, MS menggunakan drama debat antara tokoh adat (Pamenan) dengan penyiar Islam (Hudzail). Dalam drama adu argumen selama satu malam ini tentu saja semua argument adat adalah sesuatu yang ketinggalan jaman, sementara ajaran Islam adalah sesuatu yang baru dan rasional. Melalui proses inilah kemudian masyarakat memeluk Islam. Apakah proses masuknya Islam secara damai terjadi melalui suatu argumentasi rasional? Benarkan proses singkat yang penuh drama bisa mengubah keyakinan seseorang? Bukankah keyakinan seseorang berakar kuat beyond rasio? Islam (shiah) memang masuk ke Tanah Minang secara damai. Namun saya yakin masuknya Islam dengan damai ini melalui proses yang lambat dan penyerapan nilai-nilai Islam secara gradual. Beberapa buku sejarah berpendapat bahwa Islam shiah masuk Sumatra (Barat) pada abad 13 yang dibawa oleh orang-orang Persia.
Ada lagi pertanyaan yang muncul saat saya membaca novel ini. Apakah perjumpaan dengan Islam damai dan Wahabi terjadi dalam satu generasi? Dalam novel ini dikisahkan bahwa pengislaman Paninjauan terjadi di era kedatangan Hudzail. Peperangan antara kaum adat (yang sudah memeluk Islam shiah) dengan kaum Paderi juga terjadi di era Hudzail. Apakah memang sependek itu masanya? Jika hanya dalam satu generasi, apakah memang para kaum adat ini sudah benar-benar memeluk Islam (shiah?).
Alur dan plot novel ini mengalir lancar. Bahasa yang digunakan juga enak untuk dinikmati. Beberapa ungkapan dan bahasa Minang mewarnai novel ini. Penggunaan ungkapan dan bahasa Minang ini membawa pembaca kepada suasana Minang sebagai lokasi cerita. Namun ada hal-hal yang saya rasa menggangu di novel ini. Kadang-kadang ada ungkapan yang menurut saya kurang memperhatikan masa. Misalnya di halaman 9 ada istilah Jumat Kliwon yang saya yakin tidak dikenal di Minangkabau di era Paderi. Ada lagi di halaman 34 saat Datuak Sati yang belum memeluk Islam tetapi menggunakan kalimat: “Saya tidak akan menjilat ludah…munafik dan khianat.” Contoh lainnya adalah pertanyaan tentang mengapa orang Paninjauan mempertanyakan mengapa Masjid harus menghadap ke barat, bukan menghadap Patung Liberty (hal. 99). Pemilihan kata, istilah yang kurang tepat seperti di atas saya temukan di banyak tempat (Ponari hal. 17, core 2 duo hal. 90’ dan sebagainya).
Sebagai sebuah novel sejarah, “Api Paderi” ini menurut saya telah berhasil menggugah pembacanya untuk merenungkan kembali definisi pahlawan. Setidaknya bagi saya. Pahlawan bukanlah sosok yang tak bercacat cela. Meski ada sisi gelap dalam hidupnya, karya terbesar yang pernah dilakukan oleh seseorang atau sebuah gerakan tetaplah harus dihargai nilai kepahlawanannya. Sisi gelap sang pahlawan tak perlu disembunyikan. Sebab dengan mengungkap sisi gelap tersebut, maka kita menjadi semakin mengerti sosok pahlawan tersebut seutuhnya.
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.