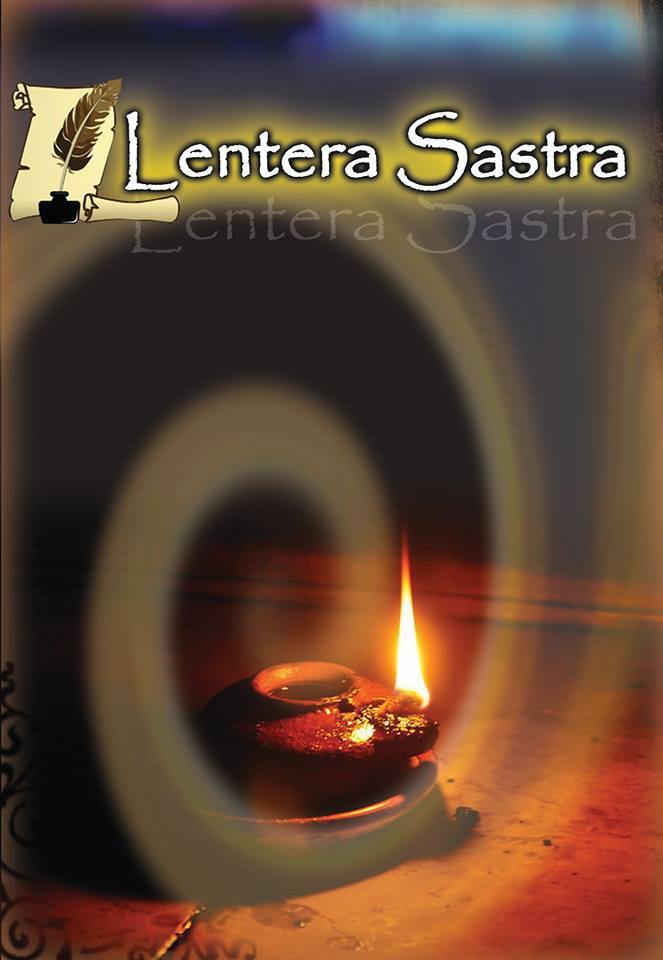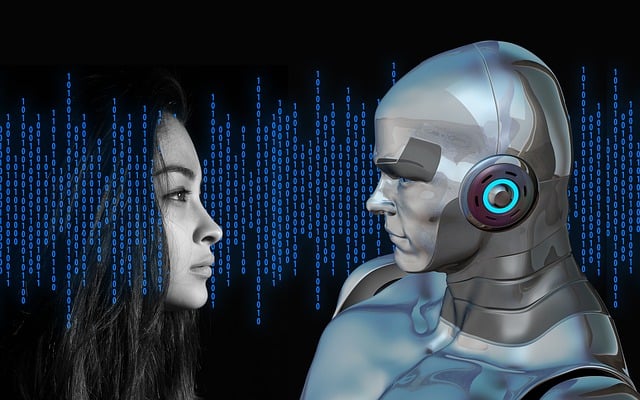LELAKI PENGENDARA ANGIN
ku-kukuh makna tabir
langit kata-kata berbunga
doa. kelopak ayat luruh
satu helai
satu helai
tanah membasah
jejak makin terbenam
ingin kurentang kepak
mengitari matahari
yang ‘tlah enggan
nyala.
–mungkin kau
sedang mengambang di sana–
tetapi tubuhku tak bergerak
rindu makin gelap,
makin pekat
mataku yang senantiasa mencarimu
kosong
barangkali desir angin deras itu
yang membawamu pergi
ke galur-galur takdir yang lain.
terarah menjauh dari
tanah penantianku yang purba.
selamat mengendarai angin, kekasih
aku tetap di sini
menanti waktu dan angin lain datang
mengarahkan takdirmu
kembali kepadaku
Pontianak, 16 Oktober 2015
(Julia Asviana, Musim dalam Angin)
I/
Pengertian cinta terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Dari pengertian yang sangat profane, dangkal, dan apa adanya hingga pada pengertian yang transenden yang butuh pendalaman yang serius. Diberangkatkan analogi-analogi kongkret hingga pada analogi-analogi abstrak. Dari pengertian-pengertian selintas kepada tafsir-tafsir yang panjang kali lebar. Dari premis-premis gamang menuju kesimpulan yang juga gamang. Begitu panjang dan ruet jalan memaknai cinta. Sepanjang dan seruet itu jalan yang ditempuh, ketika seseorang memaparkan apa itu cinta, niscaya ia akan mengecewakan banyak orang. Karena memahami “cinta” sesungguhnya bukanlah dengan mendefinisikannya.
Jalan cinta manusia satu dengan manusia yang lainnya sangat berbeda, meski kadang, dengan cara yang sama. Misalnya seorang remaja memaknai cinta sebatas hubungan seorang lelaki dengan perempuan yang kasmaran. Jalan cinta yang ditempuh juga sebatas bagaimana mengekspresikan cinta dengan cara menyatakan dan mendapatkan cinta yang sebatas formalitas ala remaja. Berbeda dengan seorang ibu yang memaknai cinta sebagai pengorbanan seumur hidup. Di mana ia harus menerima rasa sakit melahirkan, penderitaan saban malam terjaga karena tangisan, dan tua dengan kekhawatiran akan nasib anak-anaknya sambil merasakan betapa menyiksanya menggenggam cinta dalam kesepian ketika anaknya satu persatu meninggalkannya. Berbeda pula dengan jalan cinta yang ditempuh oleh seorang filsuf. Misalnya Rumi, di mana ia memaknai cinta sebagai “sesuatu” yang transenden, hingga orang-orang Barat, termasuk F. C. Happold (1960), menokohkan Rumi sebagai tokoh mistisisme cinta. Meski, bagi saya, hal-hal yang transenden tidak melulu perlu dimasukkan dalam kelompok mistisisme.
Dalam kaitannya, kini, saya membaca kumpulan puisi bertajuk Nyanyian Angin di Dada Musim karya Julia Asviana. Melalui kumpulan puisinya tersebut, rute perjalanan penyair perempuan yang tinggal di Pontianak ini dapat dijejak. Perjalanan yang dimaksud berupa perjalanan batin seorang perempuan yang penyair yang memungkinkan keluar dari konsep dimensi dunia, perjalanan badan sebagai manusia yang berada dalam dimensi ruang dan waktu, dan perjalanan akal serta nalarnya yang dimungkinkan berada di antara perjalanan batin dan badan. Dari sekian banyak jalan yang dilalui Julia, yang juga harus dilalui pejalan lain (baca: pembaca), ada peta yang terarah kepada arti sebuah nama, yang tidak lain adalah nama penyairnya sendiri, Julia. Sebagaimana dalam kutipan beberapa puisi berikut ini:
…
Di balik bulan tujuh. Angka awal romantis kulukis
bersama gerimis ritmis.
Debar serupa laut tak berpenghalang,
menyusup seperti angin dingin.
Kita di baku karang merangkai kembang laut,
—bahkan bintang saling bergoyang—
di atas gelombang bulan.
…
(Sajak Juli)
sabtu, desaunya masih berkutat.
mimpi yang kutitipkan
pada jumat malam berwarna violet(a)
dupanya, aromamu rindu.
sekelebat saja kau hadirkan seraut wajah
lalu lenyap diboyong
bayang
…
(Julia)
–
Juli
Ungunya rindu
Lelapkan deru angin:
Ihwal pecahnya nama musim
—Anak-anak yang tersenyum dan patah itu.
Angkasa taburkan empat bilah wangi pipi.
Sehelai gambar jatuh di ujung takdir.
Violet senja merengkuh masa
Ingin mendekap sah terikat.
Aku arungi lagi bahtera.
Nyanyian sepi kita
Akhirnya di sana.
…
(Julia Asviana)
Membaca puisi-puisi di atas, seketika saya teringat kepada ungkapan yang sudah sangat populer: apalah arti sebuah nama. Ternyata Julia tidak sepaham dengan ungkapan populer itu. Ia menganggap nama sebagai “sesuatu” yang penting, punya arti. Sehingga ia menjadikan namanya sebagai jalan untuk menemukan jawaban dari kegelisahan-kegelisahannya tentang waktu, yang di dalamnya disematkan mimpi sebagaimana dicerminkan dalam puisi “Julia”: “sabtu, desaunya masih berkutat./mimpi yang kutitipkan/pada jumat malam berwarna violet(a)/dupanya, aromamu rindu”. Bahkan pada “Sajak Julia” ia berusaha menemukan jalan menuju kesadaran manusia sebagai entitas yang personal dan komunal: “Kita di baku karang merangkai kembang laut,/—bahkan bintang saling bergoyang—/di atas gelombang bulan.” Selain itu, ia juga membuat puisi akrostik atas nama lengkapnya, “Julia Asviana” yang menunjukkan kesadaran akan muasal manusia dan kemana manusia akan berpulang: “Aku arungi lagi bahtera./Nyanyian sepi kita/Akhirnya di sana.”
II/
Jalan cinta Julia tidak hanya sampai pada pencarian diri di dalam diri atau di luar diri. Ia juga kerap menunjukkan keakraban antara jalan cinta dengan kerinduan. Jalan cinta dengan kerinduan ini kebanyakan bernuansa sunyi dengan menggandeng simbol alam batin yang meliputi rasa dan perasaan. Hampir semua keadaan dimaknai sebagai jalan sunyi yang panjang. Karena tidak ada jalan yang lebih panjang dan melelahkan selain jalan kerinduan. Di mana kerinduan selalu mempertanyakan jarak dan waktu yang tidak pernah memberikan kepastian. Ketidakpastian barangkali dapat disamakan dengan bilangan tidak terhingga. Tidak ada yang dapat dihitung dalam jumlah. Dan dalam ketidakpastian itu, jiwa manusia yang riuh senantiasa berhadap-hadapan dengan kesunyian yang aneh, sebagaimana begitu terasa dalam penggalan dua puisi berikut ini.
Sudahkah kau bayangkan
betapa pertemuan kita kelak, kekasih?
Saat itu,
sebagian kata-kata
mungkin telah engkau lupa.
…
(Retorika Rindu)
…
entah kapan tertaut
waktunya lalai kutuliskan
pada denah rindumu
dirinya memujimu tiada henti
seperti kepakan walet
menyambar embun
memahat senja
…
(Tautan Suara)
Pada puisi “Retorika Rindu”, ada pertanyaan retoris yang teksnya biasa saja, tapi memiliki jangkauan makna yang tidak biasa: “Sudahkah kau bayangkan/betapa pertemuan kita kelak, kekasih?”. Kata “kelak” berarti menunjukkan waktu yang akan datang. Karena ianya merupakan masa depan yang masih misteri, bisa jadi waktu itu datang bisa jadi tidak sama sekali. Pertanyaan sederhana ini akhirnya tidak sekadar pertanyaan. Terasa sekali nuansa kegetirannya. Ada tragedi di dalamnya. Pertanyaan yang datang dari seseorang yang telah lama menanti dan bertarung dengan kerinduan-kerinduannya sendiri. Penantian yang telah lama ini dapat dilihat dari larik berikutnya: “Saat itu,/sebagian kata-kata/mungkin telah engkau lupa.”. Karena yang paling memungkinkan seseorang melupkan sesuatu yang penting adalah waktu yang begitu lama.
Mengenai kata apa yang dilupakan, pembaca hanya bisa menerka. Karena penyairnya dengan sengaja menyembunyikan kata-kata apa yang dimaksud. Kalaupun hendak dimaknai secara umum, dimungkinkan sebuah janji yang, kata lagu dangdut: “siang kunantikan dan malam aku mimpikan”.
Tidak jauh berbeda dengan “Retorika Rindu”, puisi “Tautan Suara” juga menghadirkan pertanyaan. Bedanya, pertanyaan yang diajukan bukan berupa pertanyaan yang betul-betul menunjukkan keraguan, ditunjukkan dengan kata pembuka “entah”. Meski ragu, nyatanya puisi tersebut masih mempertanyakan “kapan”, yang artinya masih menyimpan harapan pada waktu. Terlebih, ada tokoh lain yang dihadirkan selain “aku” dan “kamu” di dalam puisi itu, yakni “dia”: “dirinya memujimu tiada henti/seperti kepakan walet/menyambar embun/memahat senja”. Tokoh “dia” yang dimunculkan sebagai tikaian dan tegangan dalam puisi ini, menunjukkan adanya perasaan segitiga. Entah semacam dalam sinetron atau lebih dari sekadar itu.
Selain yang kegelisahan jalan menemukan diri dari nama dan kerinduan yang panjang dan melelahkan, Julia—sebagai penyair yang telah menjadi ibu dari anak-anaknya—menelusuri jalan cinta bagi anak-anaknya. Sebagaimana dalam petikan puisi yang ia ciptakan di hari lahir putrinya: “Pagi di tubuhmu hai buah hatiku/tanam tunas terpuji selagi sejuk kulitmu/hari ini adalah tangga pengantarmu”. Selain itu, ia juga meneroka jalan cinta menuju Gusti Allah. Jalan cinta tidak mudah karena harus mampu memalingkan wajah dari cahaya-cahaya dunia yang silau dan palsu. Bacalah penggalan puisi “DemiMu”: “Yang teruntuk se-ruang-ruh; digambar jasad/Asa searus tunggal huruf; sealif asma-Mu/Rapal do’a dibaca; meng-gulir tasbih zaman”.
III/
Sebagai seorang penyair, tentu diluar semua jalan cinta yang tertera di dalam puisi-puisinya, ada jalan cinta yang sungguh-sungguh berkaitan dengan penyairnya. Yakni, jalan menekuni dunia kepenyairan. Khalayak umum yang selama ini selalu asyik sendiri dengan pertanyaan, mengapa penyair perempuan tidak begitu muncul di permukaan dibandingkan penyair-penyair lelaki, sepertinya lupa bahwa penyair perempuan dari zaman ke zaman selalu lahir. Persoalan muncul atau tidaknya di permukaan, itu bisa jadi persoalan pilihan atau kesempatan.
Jika pilihan, penyair perempuan memilih menjadi penyair yang hidup dalam kehidupan, tidak melulu hidup di dalam dunia eksistensi kepenyairan. Jika kesempatan, berarti tinggal bagaimana memberikan kesempatan lebih kepada para penyair perempuan. Sebagaimana sastra Indonesia telah memberikan ruang kepada N.H Dini, De Kemalawati, Dheknok Kristianti, Ulfatin CH, Medy Loekito, Diah Hadaning, dan lainnya, kini Julia Asviana, penyair perempuan yang rutinitasnya sebagai orang kantoran ini, telah turut hadir di tengah kesusastraan Indonesia dan perlu diberi ruang.
Dengan segenap cintanya ia telah menghadirkan puisi-puisi yang layak baca. Sebuah jalan yang tidak mudah dilalui manusia, karena yang tersulit dari penyair bukan menciptakan puisi, tapi menabahi puisi sebagai jalan yang harus ditempuh dengan segenap kesadaran bahwa penyair dan puisi adalah jalan hidup, bukan keisengan atau sesuatu yang didorong oleh napsu untuk dikenal sebagai penyair. Tentu saja tidak ada gading yang tidak retak dan bukankah keindahan gading terletak pada retakannya?
Banten, 21 Februari 2016
*) Muhammad Rois Rinaldi, penyair. Ia dinobatkan sebagai Penyair Terbaik Asia Tenggara 2015 oleh E-Sastera Malaysia dan menerima Anugerah Utama Puisi Dunia dari Nusantara Melayu Raya. Email: rois.rinaldi.muhammad@gmail.com.
Ikuti tulisan menarik Lentera Sastra lainnya di sini.