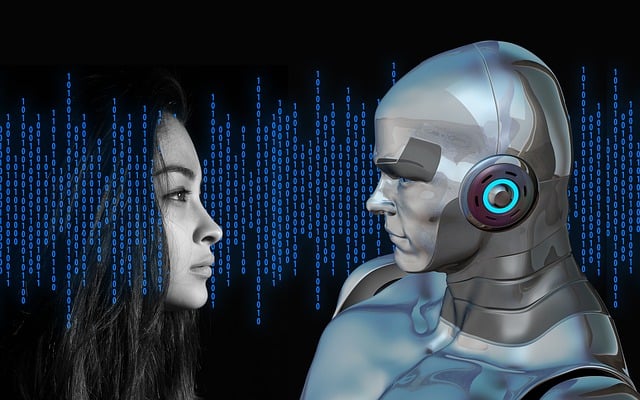Ada-ada saja kejadian di republik in. Demonstrasi bisa saja terjadi oleh hal-hal kecil yang bersifat personal seperti yang terjadi di Bengkulu. Gara-gara seorang dokter yang berdebat dengan Ketua DPRD Lebong yang berujung penamparan, lalu beramai-ramai dokter lainnya mendemonstrasikan tuntutannya agar si penampar diproses secara hukum. Mungkin baru kali ini ada demonstrasi yang disebabkan urusan pribadi, karena yang ditampar dan yang menampar sama-sama dalam kondisi emosi. Padahal, unjuk rasa atau demonstrasi biasanya lebih disebabkan urusan publik atau paling tidak memiliki ekses besar kepada keadilan publik, tidak semata-mata urusan pribadi. Jika soal tamparan saja sudah menjadi urusan publik, sedemikian parahkah hukum kita? Buktinya mereka yang berdemo sudah kehilangan kepercayaan pada proses penegakkan hukum.
Rasa-rasanya, memang hukum di negeri ini sudah sulit dipercaya. Bisa dibayangkan, berapa banyak orang berdemonstrasi menuntut berbagai proses hukum dipenuhi dari yang sekadar masalah pribadi hingga publik. Tidak hanya itu, mereka yang tertangkap tangan sebab korupsi juga masih diberi kesempatan untuk membela kesalahannya melalui mekanisme yang disebut praperadilan. Orang dituduh bersalah oleh lembaga penegak hukum, masih bisa berkelit dan tak terima atas implikasi hukum yang dituduhkan kepadanya. Padahal, semangat penegakkan hukum (law enforcement) selalu hingar-bingar diteriakkan sebagai prasyarat sebuah negeri demokrasi yang berkeadilan.
Mungkin ada benarnya, bahwa kondisi bangsa saat ini belum masih bisa dilepaskan dari berbagai rentetan sejarah masa lalu yang masih melekat dan sulit dilepaskan. Berbagai tekanan dari rezim lama yang otoriter, sepertinya membuat kondisi masyarakat belakangan semakin meledak-ledak. Disulut isu agama atau komunisme saja, lantas bersikap reaktif bahkan represif, turun ke jalan-jalan menumpahkan segala asa dan emosinya yang selama ini tak tersalurkan. Lihat saja misalnya, demonstrasi soal diskusi pengungkapan sejarah 1965 di YLBHI sedemikian hebat, sampai-sampai tidak lagi menyoal urusan tampar-menampar tetapi sudah tak peduli lagi jika harus gebuk-menggebuk. Persoalan hukum kenyataannya bukan berada di wilayah lembaga kepolisian atau peradilan, tetapi prosesnya harus dimulai dari jalanan terlebih dahulu.
Tak berlebihan rasanya, jika kita nyatakan bahwa masyarakat sekarang ini cenderung reaktif. Persis seperti halnya ketika bensin disulut bara api. Walaupun setelah terbakar, semua nampak kering, tak berbekas seperti tak pernah terjadi apa-apa, bahkan mungkin bau bensin-nya pun tak lagi terasa. Benarkah kenyataan terlampau reaktif masyarakat saat ini terkait dengan ekses otoritarianisme selama puluhan tahun dibawah rezim Orde Baru? Ah, lagi-lagi kepemimpinan Soeharto yang selalu dituduh sebagai kambing hitam, seakan tak henti-hentinya tuduhan terhadap rezim Orde Baru sebagai “biang kerok” kemunduran bangsa. Dari soal pemerintahan, afiliasi politik, bahkan hingga soal film jika itu terkait dengan penguasa waktu itu, jelas tak pernah ada benarnya. Wajar saja, jika masyarakat ikut-ikutan mudah menjadi penghujat, penuduh atau penyebar kebohongan.
Tapi, konon katanya bahwa negeri yang sedang transisi demokrasi selalu saja dihadapkan oleh persoalan-persoalan bangsa yang tak kunjung selesai, timbul tenggelam tak pernah menentu. Kedewasaan politik harus dibayar oleh bangsa ini melalui serangkaian kegaduhan, kekisruhan atau bahkan maraknya demonstrasi walaupun hanya mengangkat isu sepele. Tapi, benarkah harus demikian? Menjadi demokratis harus “membeli” dengan harga mahal, susah payah, bahkan membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun, untuk sekadar memperoleh nuansa masyarakat yang lebih demokratis dalam hal sosial, hukum dan politik.
Jepang, saya kira dapat menjadi contoh negara terdekat yang pernah terpuruk bahkan hancur berantakan ditimpa ekses perang dunia kedua. Pada 1945, Jepang dilanda keterpurukan akibat Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh sekutu pada waktu itu. Pemerintahan Jepang waktu itu, jelas otoriter apalagi diklaim sangat militeristik, sebagaimana digambarkan dalam film-film berbau sejarah yang melibatkan penjajahan Jepang atas bangsa lain. Lalu, berapa lama Jepang bangkit menjadi negara maju dan diperhitungkan oleh dunia? Mungkin hanya butuh waktu beberapa puluh tahun saja, Jepang kini menjadi negara maju dan penduduknya tak lagi terbelakang seperti dulu. Disaat kita masih menyoal isu Orde Baru, penistaan agama, atau kebangkitan komunisme, Jepang sudah melupakan masa lalunya, menatap kedepan dan bersaing dengan negara industri lainnya yang sudah terlebih dahulu berkembang dan maju.
Kita masih cenderung dihadapkan pada persoalan masa lalu yang sepertinya sulit sekali diselesaikan. Masa lalu seringkali dibawa-bawa ke masa kini, diperdebatkan, ditulis, diopinikan dan disebarkan melalui media sebagai informasi “pengingat” yang harus menggugah rakyat. Begitu mudahnya kita marah gara-gara teman kita ditampar, dihina, dicaci atau difitnah, padahal kita sesungguhnya “ditampar” bangsa lain agar diam dan tetap dalam kondisi keterbelakangan dan ketertinggalan. Ditampar bangsa sendiri kita marah, tetapi justru merasa tenang “ditampar” bangsa lain. Kenapa kita tak pernah merasa “ditampar” oleh Jepang, Malaysia, Korea atau Tiongkok? Jika “tampar” dalam arti kiasan adalah “sesuatu (peristiwa/kejadian) yang tidak mengenakkan hati”, maka cepatnya kemajuan Jepang dan negara-negara lain seharusnya menjadi “tamparan” bagi kita.
Peristiwa mendemo penampar yang digelar oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena rasa solidaritas kepada sesama profesinya, semakin menunjukkan rendahnya kualitas bangsa ini sekadar menuntut hukuman penampar yang tak mempunyai dampak apapun untuk perubahan negeri ini. Menghukum penampar tak akan merubah bangsa ini menjadi sadar atau taat hukum, atau segala urusan yang dijalankan melalui serangkaian demokrasi jalanan tak akan pula mempercepat negeri ini memperoleh kemajuan seperti yang diperoleh Jepang. Kita ini terlampau sibuk mendemo “penampar” dan kita dilupakan oleh banyaknya “tamparan” yang ditunjukkan melalui berbagai kemajuan yang diperoleh bangsa lain. Lucunya, kita juga tampak tersihir oleh ungkapan “menggebuk” yang ditujukan bagi mereka yang melanggar aturan hukum. Jangan sampai bangsa ini maju dalam urusan “menampar” atau “menggebuk”, lupa bahwa kita “ditampar” bahkan “digebuk” bertubi-tubi oleh kemajuan bangsa-bangsa lain.
Kredit foto: bengkuluekspress.com
Ikuti tulisan menarik SYAHIRUL ALIM lainnya di sini.