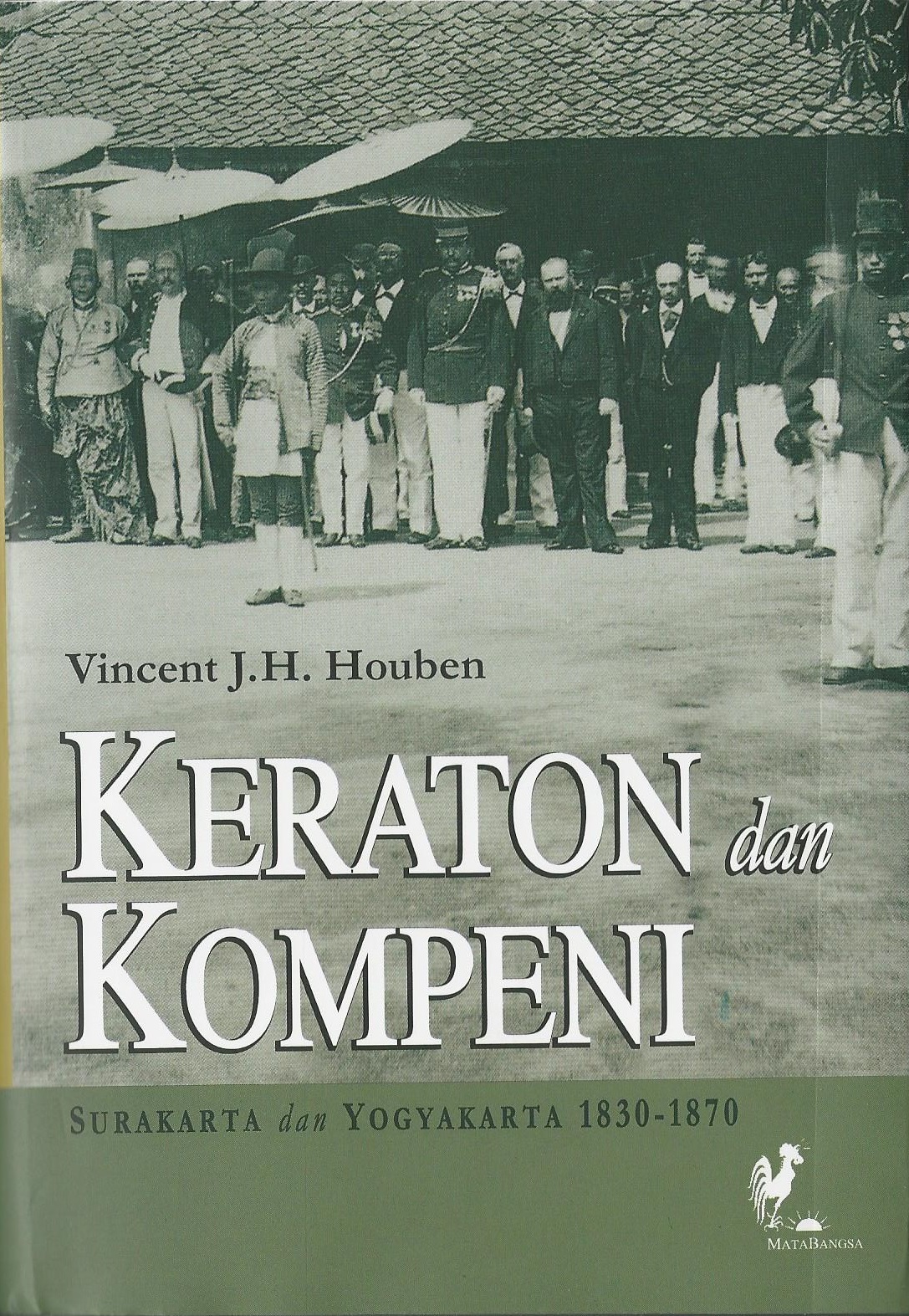Judul: Keraton dan Kompeni – Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870
Judul Asli: Kraton and Kumpeni – Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870
Penulis: Vincent J.H. Houben
Penterjemah: E Setyawati Alkhatab
Tahun Terbit: 2017 (cetakan kedua)
Penerbit: Mata Bangsa
Tebal: xix + 731
ISBN: 978-979-9471-38-3
Perang Jawa – ada yang menyebutnya Diponegoro, tahun 1825-1830 menyadarkan Belanda untuk lebih serius menguasai keraton-keraton di Jawa. Menguasai dua keraton di Jawa adalah cara paling efektif untuk mengeruk keuntungan dari suburnya tanah di Pulau Jawa. Politik devide at impera yang sudah dijalankan sejak jaman VOC, dan terbukti berhasil, kembali digalakkan oleh Gubernur Van den Bosch. Di jaman VOC, pendekatan devide et impera ini telah terbukti berhasil menguasai pantai utara Jawa pada tahun 1749 dan memecah keraton Mataram menjadi keraton Yogyakarta dan Surakarta pada tahun 1755. Belanda kembali menggunakan pendekatan devide at impera pasca perang Jawa.
Setelah Diponegoro berhasil ditangkap pada tanggal 28 Maret 1830, upaya untuk menganeksasi habis-habisan dua keraton ini muncul. Pemerintah Hindia Belanda mengutus 3 komisaris untuk menyelesaikan persoalan pasca perang. Ketiga komisioner tersebut adalah P. Merkus, J. L. Sevenhoven dan H.G. Nahuys. Gagasan penaklukan keraton Yogya dan Solo beragam. Ada yang mengusulkan supaya kekuasaan diambil total (misalnya Komisaris Van Sevenhoven) dan ada yang menyarankan untuk mempertahankan kepemimpinan Sunan dan Sultan tetapi dengan kekuasaan dan wilayah terbatas (Komisaris Nahuys dan Merkus). Pendekatan kedua inilah yang akhirnya dipakai oleh Pemerintah Van den Bosch dalam menaklukkan dua keraton yang ada di Jawa tersebut.
Politik yang dilakukan Belanda terhadap kerajaan-kerajaan Jawa semata-mata hanyalah bagian dari sebuah keseluruhan (tujuan) yang lebih besar. Mengamankan ‘tanah-tanah taklukan’ menuntut adanya perlindungan terhadap kepentingan bangsa-bangsa yang menjadi sasaran. Para penguasa Jawa secara pribadi terlalu lemah untuk ditakutkan, tetapi sekaligus cukup kuat untuk mendukung tujuan-tujuan Belanda. Sekali para penguasa dan pangeran-pangeran itu dijamin sepenuhnya dengan uang dari pemerintah, mereka akan sepenuhnya tergantung kepada Belanda. Dengan sedikit martabat kebangsawanan tersisa di tangan, mereka tidak akan pernah mau merendahkan diri mengikuti rakyat jelata untuk memberontak (hal. 94)
Houben menjelaskan strategi Belanda paska perang Diponegoro. Dengan memanfaatkan kehancuran keraton, khususnya Yogyakarta, Belanda melakukan negosiasi pengambil-alihan wilayah mancanegara dengan imbalan pendapatan bulanan yang pasti kepada Sunan dan Sultan serta para pangeran (hal. 30). Politik Batavia adalah dengan membuat keraton tergantung secara finansial dan menghindari semua masalah yang bisa menyinggung keraton (hal. 141). Untuk menyenangkan Sunan dan Sultan serta para pangeran, Belanda memberikan embel-embel dan pangkat militer (hal. 142) dan melakukan kunjungan resmi para pejabat Batavia ke keraton-keraton tersebut. Selanjutnya Belanda menggiring bangsawan keraton ke dalam peran tradisi ritual sehingga mereka benar-benar terkunci di dalam keratonnya sendiri (hal 223).
Motif sesungguhnya dari Belanda dalam pengambil alihan wilayah mancanegara ini adalah ekonomi. Houben mengatakan bahwa “Argumen Belanda perihal mengapa Yogya dan Solo harus menyerahkan daerah-daerah yang begitu luas, yaitu demi ketenteraman dan kemakmuran rakyat sesungguhnya agak dibuat-buat dan berlebihan. Luasnya aneksasi wilayah itu memiliki tujuan politik dan ekonomi bagi Belanda yang ingin melucuti kekuatan dan kekuasaan pada penguasa Jawa dan mencegah, untuk selama-lamanya terjadinya perang Jawa kedua; keduanya menuntut agar para penguasa Jawa tetap dipertahankan demi melegitimasi kekuasaan Hindia Belanda di mata rakyat Jawa. Pada saat yang sama, Pemerintah Hindia Belanda ingin meningkatkan pendapatan mereka secara dramatis, dengan cara mengambil alih eksploitasi atas mancanegara yang subur dan kaya itu (hal 116).
Keraton Yogya yang sudah luluh lantak karena perang dan secara internal terpecah belah dan nyaris tak bisa menolak rencana-rencana Belanda. Lain halnya dengan Solo. Keraton ini lebih sedikit menderita akibat perang (115). Itulah sebabnya negosiasi pengambil-alihan wilayah-wilayah Solo (Madiun dan Kediri) lebih alot daripada wilayah Yogyakarta (Begalen dan Kedu). Jika Yogyakarta menyerahkan tanah-tanah mancanegara dengan mudah tanpa syarat, Solo mensyaratkan martabat dan penghormatan kepada Sunan dari wilayah mancanegara tetap dipertahankan.
Pengambil-alihan tanah-tanah keraton tidak berhenti sampai dengan diserahkannya wilayah-wilayah mancanegara. Pada tahun 1831, Belanda memprakarsai penyerahan wilayah Nanggulan dan Kalibawang kepada pangeran-pangeran. Namun setelahnya, kedua wilayah ini diambil kembali. Kalibawang dikembalikan ke keraton, tetapi Nanggulan secara licik menjadi milik Belanda (hal 255) sebelum akhirnya dikembalikan ke Sultan; demikian juga dengan Jagarangkah dan Karangkobar (hal. 259).
Meski usulan dari Sunan Surakarta supaya kekuasaannya (martabat) di wilayah mancanegara tetap dipertahankan, yaitu dengan meminta para bupati mancanegara datang menghadap setahun sekali, tetapi pada kenyataannya hal itu tidak pernah terwujud. Terbukti sejak 1830 para bupati mancanegara tidak lagi menghadap Sunan maupun Sultan. Dengan demikian kekuasaan pemerintahan atas Jawa telah benar-benar beralih ke tangan Hindia Belanda.
Selain dengan mempersempit wilayah kekuasaan para raja Jawa, Belanda juga ikut campur dalam suksesi kepemimpinan, urusan internal keraton termasuk pengaturan keuangan dan hal penyewaan tanah-tanah apanase kepada para pengusaha partikelir di kedua keraton tersebut. Suksesi yang paling nyata disetir oleh Belanda adalah suksesi dari Hamengku Buwono (HB) V ke HB VI, dan dari Paku Buwono (PB) VI ke PB VII. Dalam urusan suksesi ini Belanda memakai prinsip legitimasi dan asas manfaat dalam menentukan calon Sunan atau Sultan. Prinsip legitimasi adalah untuk mencari pembenaran dalam pandangan orang Jawa (hal. 390). Belanda ikut mengatur/mencegah perkawinan antara calon-calon Sultan dan Sunan supaya calon yang diingini memiliki legitimasi dalam pandangan Jawa. Sedangkan asas manfaat adalah memilih calon yang bisa diajak bekerjasama dengan Belanda. Contohnya adalah pemilihan Pangeran Purboyo untuk menjadi PB VII setelah PB VI dilengserkan. Setelah tahun 1830, atau setelah perang Jawa, Belanda lebih mengutamakan asas manfaat daripada legitimasi.
Selain mengatur masalah suksesi, Belanda juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan keraton melalui hubungan informal para pejabat, tentara dan para penyewa lahan. Hubungan informal ini biasanya memanfaatkan kebiasaan buruk para pangeran, yaitu hidup berfoya-foya sehingga terjerat hutang. Pemerintah Belanda juga semakin kuat dalam menguasai keamanan dengan ijin Sultan bagi para penyewa lahan untuk mengangkat mantri-mantri polisi sendiri (hal 274).
Sejak tahun 1820, Belanda sudah ikut campur dalam mengatur penyewaan lahan milih para pembesar keraton Yogyakarta dan Surakarta. Bahkan pengaturan penyewaan tanah ini dianggap sebagai salah satu faktor pemberontakan Diponegoro kepada Keraton Yogyakarta dan melawan Belanda. Pengaturan penyewaan tanah ini bertujuan supaya produksi hasil pertanian yang diusahakan melalui Tanam Paksa tidak terganggu dengan produksi yang dihasilkan oleh pengsaha-pengusaha swasta tersebut. Pengaturan juga bertujuan supaya para kerabat keraton tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga mereka bisa mandiri secara keuangan dan tidak lagi tergantung kepada gaji bulanan yang disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Belanda khawatir kemandirian keuangan akan membuat perang Jawa berikutnya bisa terjadi.
Apakah kemudian setelah keraton Yokyakarta dan Surakarta mengempis, Belanda sudah bisa melenggang sendirian? Ternyata Belanda tetap waspada. Contohnya pertemuan tahunan antara Sultan dan Sunan di Gowok dianggap sebagai sebuah potensi yang berbahaya. Belanda kemudian memprovokasi Sultan Yogya supaya tidak menghormati “kakaknya” Sunan Surakarta. Akibatnya pertemuan tahunan ini kemudian tidak berlanjut (hal 137). Belanda juga beberapa kali berupaya menggagalkan perkawinan antar keraton yang memiliki potensi penyatuan kembali Yogyakarta dengan Surakarta.
Benar saja. Kewaspadaan Belanda terbukti bahwa ketidak-puasan diantara rakyat, pemimpin-pemimpin di pinggiran dan bahkan dari dalam kalangan keraton sendiri bermunculan. Berbagai pemberontakan dan rencana-rencana pemberontakan. Bisa dicatan di sini beberapa diantara upaya makar tersebut. Maraknya kecu di wilayah-wilayah kedua keraton ini pada akhir tahun 1860-an (hal. 404). Pemberontakan Mangkuwijaya (hal. 409) yang ingin mendirikan keraton baru di Prambanan. Larinya beberapa pangeran dari Solo (hal. 420). Pemberontakan seorang keturunan Arab bernama Syekh Prawira Sentana yang berkolaborasi dengan seorang Cina bernama Tja Bung Seng di wilayah antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto. Upaya makar Mertanegara yang didukung oleh Pangeran Suryengalaga kakek dari Pangeran Mohamad yang (diduga) adalah anak dari PB V (hal428). Belum lagi sisa-sisa laskar Diponegoro dan khususnya adik dan anak-anak Diponegoro yang masih dipercaya oleh rakyat (434). Namun semua pemberontakan dan upaya pemberontakan ini berhasil ditangani oleh Belanda.
Dalam buku ini Houben membahas cukup detail tentang pengaruh pengusaha partikelir yang menyewa lahan terhadap posisi keraton dan sosial ekonomi masyarakat Jawa. Pembahasan tentang perusahaan-perusahaan pertanian swasta yang menyewa lahan para petinggi keraton ini jauh lebih penting daripada membahas akibat Tanam Paksa di wilayah kedua keraton ini. Sebab kebijakan Tanam Paksa tidak diterapkan di wilayah Keraton Solo maupun Keraton Yogya.
Topik lain yang dibahas oleh Houben dalam buku ini adalah tentang penyewaan lahan untuk usaha pertanian swasta oleh orang-orang Eropa. Houben menyimpulkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari perkebunan swasta yang menyewa tanah-tanah ini sama pentingnya dengan akibat yang ditimbulkan oleh sistem Tanam Paksa. Menurut Houben, sistem perkebunan swasta ini telah mengubah sistem pertanian di Jawa dari pertanian pangan ke tanaman perkebunan, sama seperti sistem Tanam Paksa. Sistem perkebunan besar swasta ini dalam praktiknya juga menggunakan pengaruhnya pada para elite untuk menyerahkan tanah dan menyediakan buruh.
Dampak dari perusahaan swasta ini dipersepsikan secara beragam. Residen Yogyakarta, de Kock berpendapat bahwa ekspansi penanaman tanaman-tanaman komersial untuk pasar Eropa telah membuat kedua kerajaan itu “merosot moralnya, termiskinkan, dan sengsara.” Sedangkan Residen Solo de Geer berpendapat bahwa kemiskinan yang ditimbulkan tidak separah akibat Tanam Paksa. De Geer menyatakan bahwa sistem pertanaman padi di wilayah tanah-tanah perkebunan swasta tidak terganggu (hal. 585).
Houben menyampaikan bahwa sistem sewa tanah ini mengakibatkan tanah menjadi obyek perdagangan dan spekulasi (hal 590). Hal ini jelas mengubah peran tanah dalam budaya Jawa sebelumnya dimana pemegang tanah menggunakannya untuk berbagi hasil dengan para petani. Akibatnya struktur sosial di pedesaan Jawa juga berubah.
Sistem sewa lahan ini juga menyebabkan Yogyakarta mengimpor padi sementara Solo tetap bisa memenuhi kebutuhannya (hal. 594). Houben menemukan bahwa luasan wilayah penanaman padi turun drastis dan harga beras meningkat dengan signifikan (hal. 596). Ia selanjutnya menyebutkan bahwa sistem perusahan swasta ini membuat invasi ekonomi moneter berkembang pesat di pedesaan Jawa (hal. 605). Pengaruh lainnya adalah masifnya pembangunan infrastruktur transportasi termasuk kereta api.
Dalam pengantarnya Bambang Purwanto menyampaikan bahwa buku ini telah memberikan perspektif baru dalam kajian historiografi Jawa. Pertama buku ini menyadarkan bahwa sistem Tanam Paksa tidak pernah diterapkan di wilayah Vortstenlanden, Surakarta dan Yogyakarta (hal. viii). Kedua, keberadaan para pengusaha swasta ternyata tidak hanya berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Praja Kejawen, melainkan juga pada kehidupan politik (hal. xiii). Peran perusahaan swasta yang menyewa lahan dari para pembesar keraton ini selama ini luput dari pembahasan dalam kajian historiografi Jawa khususnya periode 1830-1870.
Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.