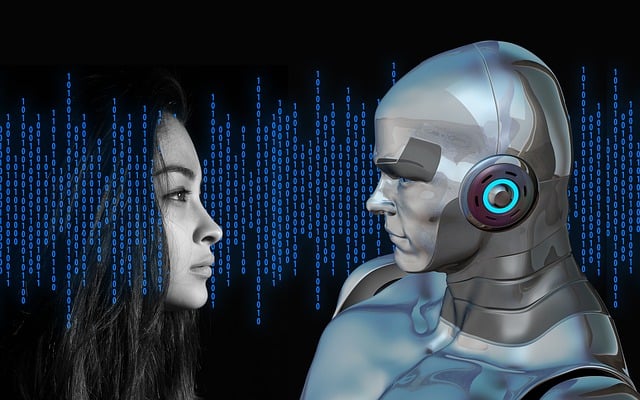Salah satu cara untuk mengetahui situasi zaman ialah dengan membaca catatan-catatan yang dibuat oleh para saksinya. Sayangnya, tidak cukup banyak orang yang tekun mencatat situasi zamannya dan menyimpan komentar dan pendapatnya mengenai zaman itu. Di antara yang sedikit itu ada Soe Hok Gie, Ahmad Wahib, dan Iwan Simatupang—meskipun Iwan menuangkannya dalam bentuk surat kepada sahabatnya, Soelarto.
Setelah 40 hingga 50 tahun berlalu, tetap menarik dan relevan untuk membaca kembali catatan pikiran mereka. Surat Iwan dan catatan Gie lebih banyak berisi komentar dan pengalaman terkait dengan situasi masyarakat dan politik tahun-tahun 1960an, menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno. Catatan Wahib, seperti diwakili judul bukunya, merefleksikan pergulatan pikiran dan batinnya mengenai isu-isu keagamaan.
Ketiganya sosok yang gelisah melihat keadaan. Tentang Gie, Nugroho Notosusanto—dosen muda di Jurusan Sejarah UI di masa itu, yang kelak menjadi Menteri Pendidikan di zaman Soeharto—berkomentar: “Dia adalah seorang jujur dan berani. Dan mengerikan, karena ia maju lurus dengan prinsip-prinsipnya tanpa kenal ampun. Maka seringkali ia bentrok karena dianggap tidak taktis.”
Surat-surat politik Iwan Simatupang 1964-1966
Buku ini memuat surat-surat budayawan Iwan Simatupang (antara lain menulis novel Kering, Ziarah, dan Kooong) dengan sahabatnya, Soelarto. Sebagaimana diwakili oleh judulnya, buku ini hanya memuat surat Iwan dan tidak memuat surat Soelarto kepada Iwan—rupanya, dalam hal dokumentasi, Iwan tidak serapi sahabatnya yang sejak awal sudah menyimpan surat-surat Iwan dengan tertib.
Seperti kata Frans Parera, yang menyunting buku ini, surat-surat Iwan telah menjadi saksi terjadinya percakapan yang terus-meneurs tentang situasi kehidupan bersama dalam perspektif budaya, yang timbul dan tenggelam dipermainkan oleh kekuasaan politik. Dari Hotel Salak, Bogor, tempat ia menetap, Iwan berbicara tentang beragam soal—khususnya menanggapi situasi politik nasional ketika itu yang kian meruncing.
Dalam suratnya kepada Larto tertanggal 7 Agustus 1965, Iwan menulis: “Apakah kita di dalam iklim begini di tanah air kita masih bisa (terus) mencipta? Kita makan tak makan; badan kurang vitamin; anak isteri murat-marit; hutang di sana-sini; sedang manusia-manusia di sekeliling kita makin asing, asing...”
Sekitar dua minggu setelah peristiwa berdarah 30 September 1965, Iwan menulis kepada Larto: “Suasana tanah air kini adalah suasana penuh conspiracy, penuh samenzwering, samenzweerderij (persekongkolan, bahasa Belanda): komplotan gelap di mana-mana. Perhatikan wajah orang-orang kini: mata mereka satu per satu liar, sebentar-sebentar melihat lekas ke suatu arah tertentu, seolah dari sana datang segera bahaya...// Suara orang sekarang tak lagi bernada penuh. Setengah berbisik, setengah menggumam...”
Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran
Soe Hok Gie, tulis Harsja W. Bachtiar—kawan berdiskusi Gie yang kelak menjadi guru besar di Universitas Indonesia, adalah cendekiawan yang ulung yang terpikat pada ide, pemikiran dan yang terus-menerus menggunakan akal pikirannya untuk mengembangkan dan menyajikan ide-ide yang menarik perhatiannya. Gie, kata Bachtiar pula, juga kerap melontarkan kecaman terhadap otoritas, dan kecaman itu dilancarkan atas pemikiran yang jujur, atas dasar iktikad baik. “Ia tidak selalu benar,” kata Bachtiar, “tapi ia selalu jujur.”
Gie tercekik oleh gas beracun kawah Mahameru, Jawa Timur, di suatu tempat yang terpencil dan dingin, 16 Desember 1969—dalam usia 27 tahun. Seperti dituturkan kakaknya, Arief Budiman, hanya seorang yang mendampingi kematian Gie ketika itu, yakni salah seorang sahabatnya yang sangat karib—Herman Lantang. Catatan harian Gie kemudian diterbitkan oleh sahabat-sahabatnya untuk pertama kali pada Mei 1983.
Dalam catatan hariannya, Gie mengomentari situasi masyarakat masa itu, tapi ia juga menuliskan renungan-renungannya. “Sejarah dunia adalah sejarah pemerasan. Apakah tanpa pemerasan sejarah tidak ada? Apakah tanpa kesedihan, tanpa pengkhianatan, sejarah tidak akan lahir? Seolah-olah bila kita membagi sejarah maka yang kita jumpai hanya pengkhianatan. Seolah-olah dalam setiap ruang dan waktu kita hidup atasnya. Ya, betapa tragisnya.”
Juga tentang hal-hal pribadi: “Pulang dari kuliah pergi ke Rina bersama Dahana. Kita ngobrol lama sekali, sampai 5 jam, mulai dari soal-soal pribadi sampai pada soal-soal Fakultas Sastra UI. Setiap orang akhirnya punya persoalan-persoalan yang melihat kehidupan pribadinya. Dahana dengan masa depannya, Rina dengan persahabatannya, dan saya dengan keragu-raguan menghadapi masa depan. Dan saya kira dengan mengenal manusia dalam detail hidupnya, kita akan lebih mencintai manusia.” (21 Agustus 1968).
Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib
Ahmad Wahib meninggal dalam usia 31 tahun (30 Maret 1973) tatkala baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai reporter—sebuah sepeda motor yang dikendarai dalam kecepatan tinggi menabraknya di daerah Senen, Jakarta. Sebelum ke Jakarta, Wahib kuliah di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Di kota ini, ia bergaul dengan para aktivis Islam dan terlibat dalam kelompok diskusi Limited Group yang dipimpin oleh Dr. Mukti Ali, yang kelak menjadi Menteri Agama. Banyak anak muda yang bergabung dalam kelompok diskusi ini dan mereka serinng terlibat diskusi tentang isu-isu keagamaan yang bagi banyak orang mengejutkan.
Mukti Ali, dalam pengantar buku ini, menulis: “Saya merasa akan sangat rugi apabila kalangan muda itu dibiarkan memendam berbagai pertanyaan dan mungkin gugatan dalam pikiran mereka, yang justeru menyangkut hal-hal yang dasar dalam agama. Mereka rata-rata berusia dua puluhan. Mereka sedang dalam proses mencari...”
Dalam catatan tertanggal 28 Maret 1969, Wahib menulis: “Aku belum tahu apakah Islam itu sebenarnya. Aku baru tahu Islam menurut HAMKA, Islam menurut Natsir, Islam menurut Abduh, Islam menurut ulama-ulama kuno, Islam menurut Djohan, Islam menurut Subki, Islam menurut yang lain-lain. Dan terus terang aku tidak puas. Yang kucari belum ketemu, belum terdapat, yaitu Islam menurut Allah, pembuatnya. Bagaimana? Langsung studi dari Qur’an dan Sunnah? Akan kucoba...”
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Wahib mungkin saja juga menjadi pertanyaan banyak orang. Namun, keberanian Wahib untuk mengutarakan kegelisahannya itu yang membuat banyak orang terkejut. (foto ilustrasi: tempo) **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.