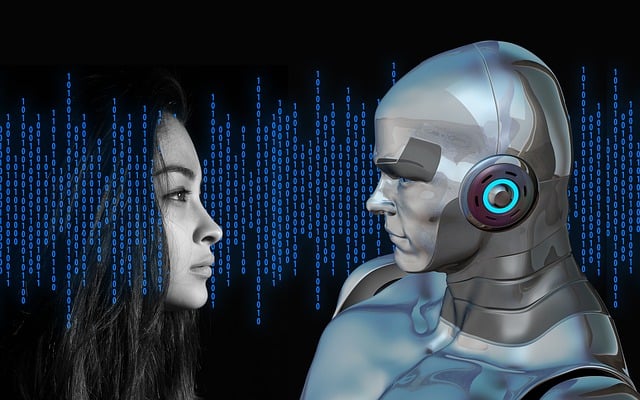Rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di mana di dalamnya termasuk menghilangkan status justice collaborator sebagai syarat bagi koruptor untuk mendapat pengurangan masa hukuman (remisi), sudah tepat. Semua syarat bagi nara pidana untuk mendapatkan remisi harus bersifat setara, dan bebas diskriminasi berbasis kesalahan.
Korupsi adalah extraordinary crime. Dampak yang timbul akibat perbuatan jahat pejabat yang memakan duit rakyat, atau pejabat menyalahgunakan wewenangnya dengan memberi kemudahan pengusaha untuk menilep uang negara, untuk mengeruk sumber daya alam, untuk menghindari peraturan perundangan, dan beberapa perbuatan tercela lainnya, sangat dasyat. Banyak yang sepakat, kondisi Indonesia saat ini, yang belum bisa beranjak dari status negara berkembang padahal kita memiliki kekayaan bumi dan laut yang sedemikian melimpah, disebabkan oleh koruptor yang bercokol di lembaga-lembaga pemerintahan baik pusat maupun daarah. Dari pejabat di pucuk pemerintahan hingga yang paling bawah.
Tentu masih banyak dampak buruk yang timbul akibat korupsi dengan segala variannya. Tetapi membedakan perlakuan antara narapidana kasus korupsi dengan kasus kejahatan lainnya, setelah vonis dijatuhkan dan yang bersangkutan tengah menjalani masa hukuman, adalah bentuk diskriminasi yang melanggar banyak hal.
Setidaknya ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, hukuman dijatuhkan sesuai perbuatannya. Lembaga peradilan- termasuk peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang menilai seberapa berat kesalahan lalu menghukum sesuai undang-undang yang disangkakan, fakta persidangan dan hari nurani hakim. Faktor subjektifitas hakim, harus dipandang sebagai hal-hal yang tidak termuat dalam perundang-undangan maupun fakta persidangan. Hal ini juga yang sering membedakan antara dua terdakwa dengan kasus dan modus operansi yang sama namun putusan hukumannya berbeda.
Kedua, konsep lembaga pemesyarakat. Pasal 2 UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi : sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Sedangkan pada Pasal 3 disebutkan : Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Dari dua pasal tersebut setidak tercermin semangat bahwa lembaga pemasyarakatan dibentuk bukan untuk balas dendam terhadap pelaku kejahatan, melainkan pembinaan terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan kesalahan (pidana). Harapannya, kelak usai menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, orang tersebut dapat kembali ke tengah masyarakat dengan kepribadian yang lebih Ketika melaksanakan hukuman di dalam lembaga pemasyarakat, terpidana tidak serta-merta kehilangan semuanya.
Negara juga menjamin adanya “bonus” bagi narapidana yang bersikap baik berupa remisi. Kelakukan baik di sini dijabarkan sebagai tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan telah mengikuti program Pembinaan yang diselenggarakan LAPAS dengan predikat baik. Remisi bersifat umum sebagai pengertian Pasal 14 ayat 1 huruf (i) UU Pemasyarakatan. Pada pasal dimaksud dengan jelas disebutkan narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana.
Dengan pemahaman itu, pembatasan remisi bagi narapidana korupsi kecuali yang bersangkutan telah menjadi justice collaborator sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, jelas diskriminatif. Apakah semua pelaku tindak pidana korupsi pasti mengetahui korupsi di tempat lain atau keterlibatan pihak lain dalam korupsinya? Bagaimana dengan kasus koruptor yang pelakunya tunggal? Contohnya, kepala proyek pemerintah yang menilep anggaran. Dari berbagai fakta yang ada, uang itu diambil dan pergunakan untuk dirinya sendiri tanpa pelibatan orang lain, baik atasan, bawahan maupun mitra kerja (kontraktor). Bagaimana mungkin dia bisa menjadi justice collaborator? Jika sudah begitu, di mana fungsi lembaga pemasyarakat dan prinsip keadilan jika dia tidak mendapat remisi padahal sudah divonis sesuai perbuatannya, sudah meneysali perbuatan, sudah bertobat dan berkelakuan baik?
Dari pada menolak revisi tentang remisi, akan lebih produktif jika kita mendorong agar kejahatan korupsi dinyatakan (di dalam undang-undang) sebagai kejahatan luar biasa alias extraordinary crime sebagaimana kejahatan narkoba dan terorisme. Dengan label itu maka koruptor bisa dikenakan hukuman maksimal yakni hukuman mati, bukan hanya ancaman hukuman seumur hidup sebagai dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.
Faktanya, baru mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang divonis seumur hidup, sementara lainnya paling tinggi divonis 18 tahun. Hal ini yang sebenarnya mencederai rasa keadilan masyarakat. Koruptor yang hidup bergelimang uang negara, divonis “ringan”, padahal kejahatannya telah merusak satu generasi, memupus harapan anak banyak, membuat sengsara masyarakat.
Kita harus menolak peraturan diskriminasi dalam hal apa pun. Sekali kita permisif pada hal itu, maka ke depan akan semakin banyak UU, peraturan pemerintah, bahkan peraturan daerah yang berlaku demikian. Mari kita pahami esensinya, bukan sekedar artifisial demi popularitas sambil mematikan logika masyarakat.***
Ikuti tulisan menarik yon bayu wahyono lainnya di sini.