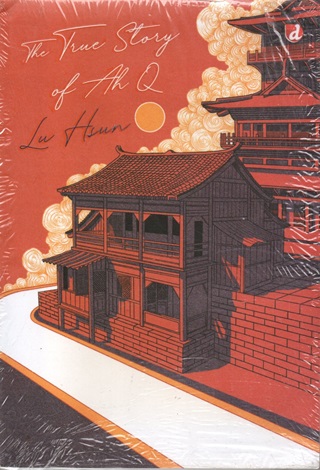Ada paradoks dari dua rencana proyek yang sedang menjadi sorotan sosial saat ini. Pertama, normalisasi Ciliwung yang merupakan proyek dibawah kendali Pemprov DKI Jakarta. Kedua, Reklamasi atau -sebut saja- abnormalisasi Teluk Jakarta, yang meski berada juga di Jakarta namun menjadi megaproyek yang melibatkan hierarki yang lebih kompleks, selain Pemprov DKI Jakarta.
“Segala sesuatu diciptakan saling berlawanan”, Begitulah bunyi konsep dualisme dari Pythagoras, yang seakan ingin mematahkan dua konsep sebelumnya yang lebih dulu eksis dalam filsafat ontologi, yaitu Idealisme dan Materialisme.
Seperti normalisasi dan abnormalisasi, saling berlawanan. Sedangkan masing-masing kata yang mengikutinya, yaitu Ciliwung yang mengasosiasikan nama sungai, dan Teluk Jakarta yang mengasosiasikan laut, adalah bagian dari anonim yang bersifat hierarki murni. Sungai dan Teluk berbeda, tapi berada dalam satu kesepadanan hirarkis. Air sungai menghilir menuju laut, kemudian laut menaungi aliran dari sungai.
Normalisasi
Normalisasi sungai Ciliwung menjadi landasan bagi Gubernur DKI Jakarta untuk merelokasi, -sebuah eufemisme yang entah bertujuan diplomatis, mengaburkan makna, atau pencitraan?- puluhan keluarga di Kampung Bukit Duri. Proyek yang sempat mengalami penundaan sekian tahun tersebut disinyalir searah dengan pembangunan berwawasan lingkungan, karena bertujuan menyelamatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meski ada harga sosial yang harus dibayar, yaitu ratusan warga yang ‘dipindahkan’ ke rusun Rawa Bebek dan merintis hidup baru disana.
Proyek normalisasi sungai Ciliwung di sekitar Kampung Bukit Duri pun masih tersandung oleh proses gugatan class action dari warga. Penggusuran atau -yang dibengkokan menjadi- relokasi tersebut dianggap telah melawan hukum karena Pemkot Jakarta Selatan dalam sosialisasinya tidak pernah menyebutkan dan membuktikan bahwa tanah tersebut milik Pemprov DKI. Disisi lain, Ahok sudah melayangkan Surat Peringatan 2 (SP2) kepada warga Kampung Bukit Duri, dan bersikukuh akan melayangkan SP3 apabila warga belum juga pindah ke rusun Rawa Bebek.
Mari menengok dulu sebentar ke sejarah panjang Kampung Bukit Duri. Seperti yang ditulis Zaenudin HM dalam buku setebal 377 hal. yang berjudul “212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe” bahwa pada tahun 1686 rumah-rumah di Bukit Duri dikelilingi pagar berduri dan dijaga belasan tentara yang sakit-sakitan untuk melindungi para penebang hutan dan tukang kebun dari gerilya tentara Mataram dan Banten. Ada sedikit kesamaan sejarah, jika akhirnya warga Kampung Bukit Duri benar-benar ‘dipindahkan’ untuk melindungi Jakarta dari banjir. Di abad 16an maupun sekarang, tujuannya sama-sama untuk melindungi.
Abnormalisasi
Sedangkan Reklamasi Teluk Jakarta, baru-baru ini dicabut moratoriumnya oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Alasannya demi menyelamatkan nama baik Indonesia di mata investor asing yang kepalang berinvestasi di Pulau G. Salah satu dari 19 alasan menolak reklamasi Teluk Jakarta yang dirilis website Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta, yaitu reklamasi dapat menghilangkan fungsi daerah tampungan yang memperbesar aliran permukaan. Dengan hilangnya fungsi daerah tampungan tersebut, artinya menuju proses tidak normal. Abnormalisasi.
Disharmonis dalam Dualis
Terbaca disharmonisasi dari proyek normalisasi Ciliwung dan reklamasi Teluk Jakarta, yang satu menyelamatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang lainnya menyelamatkan citra negara di mata investor asing. Disharmonisasi tersebut mengingatkan kembali pada konsep dualisme, yang juga menganggap bahwa hal yang berlawanan bukan sebagai satu kesatuan. Saling berdiri sendiri, terpisah, dan menutup ruang bagi segala dialektika. Seperti pemisahan konsep akal dari jiwa. Maka frasa “menyelamatkan RTH tanpa mengindahkan hak-hak warga” dan “menyelamatkan citra negara meski merusak lingkungan” selaras dengan nalar dualisme. Disharmonisasi, tetapi sah karena memang tak ada yang saling terhubung, begitulah dalam dualisme.
Disadari atau tidak, kebanyakan orang sudah kadung memaklumi bunyi ketumpulan hukum di negeri ini: makin ke atas makin tumpul. Lalu, hari ini, apakah kita pun harus melatih diri untuk memaklumi hukum ketumpulan upaya penyelamatan lingkungan? Makin ke atas, juga makin tumpul?
Atau memang eufemisme sengaja digunakan dengan tujuan untuk melatih pemakluman atas semua ketimpangan? Relokasi untuk penggusurun. Reklamasi untuk abnormalisasi. Maklumi saja, begitu?
*Eufemisme: berasal dari bahasa Yunani euphemisme yang artinya berbicara baik. Eufemisme juga berarti elegan, halus, lemah lembut, meletakkan rapi dan baik yang dinyatakan. Ini dipakai untuk menyebut sesuatu yang dirasakan mengganggu atau tidak enak, agar terdengar lebih enak atau menjadi yang sebenarnya. Caranya adalah dengan mengganti kata-kata yang memiliki konotasi ofensif dengan ungkapan lain yang menyembunyikan kata yang tidak enak tersebut, dan bahkan menjadi sebutan yang sifatnya positif (Leech,2003:71).
(sumber foto: konservasidasciliwung.wordpress.com)
Ikuti tulisan menarik Diaz Setia lainnya di sini.